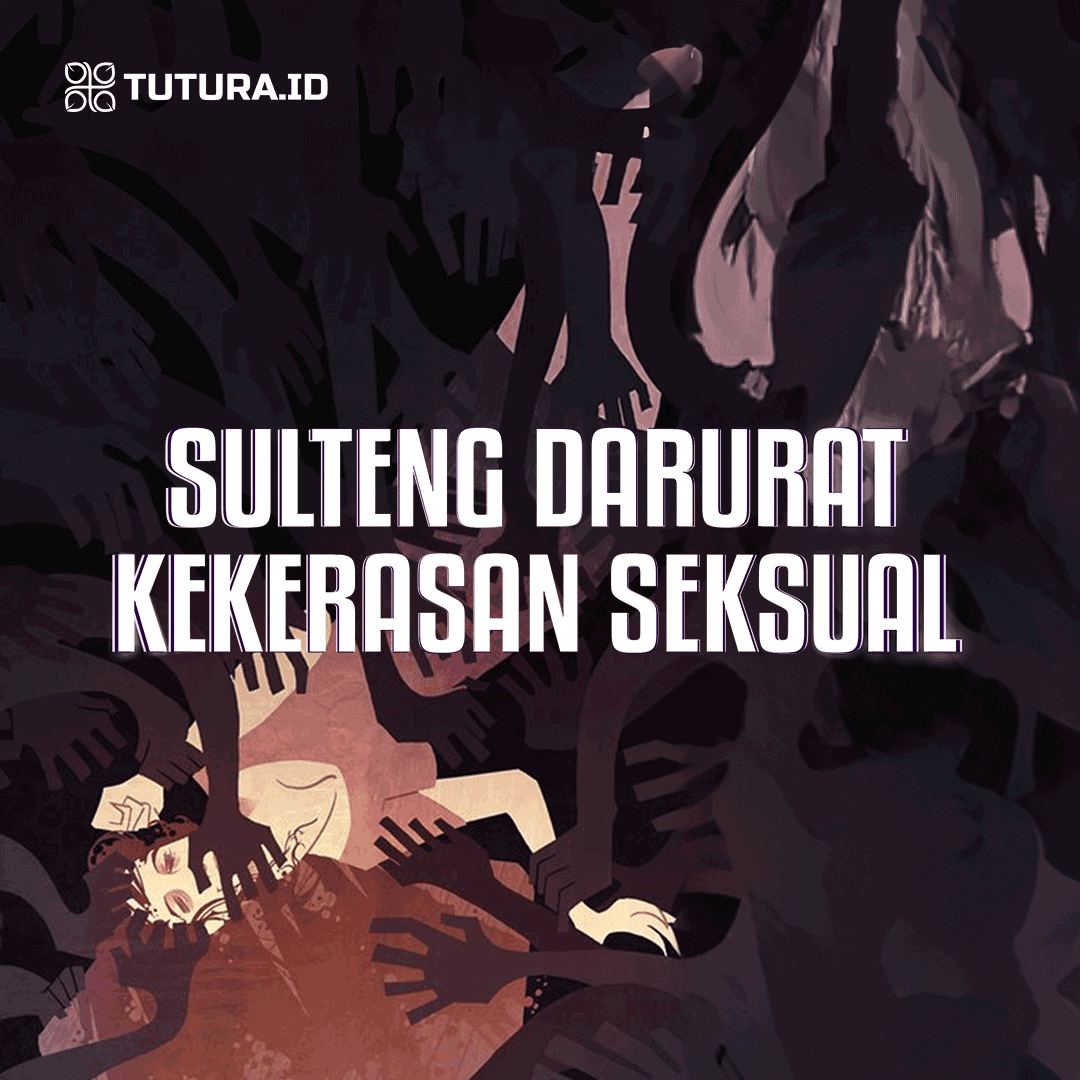Banyak orang bilang, "hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas." Pandangan itu merupakan ekspresi sosial atas penegakan hukum di Indonesia.
Pasca-merdeka, Indonesia menggunakan hukum pidana warisan kolonial. Hukum pidana inilah yang ingin diganti; tentu saja dengan dalih semangat nasionalisme.
Keinginan itulah yang akhirnya terwujud lewat pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna DPR-RI, 6 Desember 2022.
Sebagai disklaimer dalam tulisan ini, saya perlu menyampaikan bahwa saya bukanlah ahli hukum. Namun, praktek hukum telah saya ketahui baik langsung maupun tidak. Saya hanya merespons hukum pidana baru ini dengan pengetahuan yang saya miliki.
Pada 2019, hukum pidana yang saat itu masih berupa draf mulai diwacanakan akan disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun rancangan itu beroleh penolakan masif dari masyarakat, terkhusus mahasiswa. Mereka lempar kritik ihwal hak kebebasan berpendapat, hingga pasal "unggas jalan-jalan" ke kawasan permukiman.
Lantaran bersemuka penolakan, boleh jadi para pembesar berpikir dua kali buat ketuk palu RKHUP.
Barulah pada akhir 2022, hukum pidana baru ini disahkan. Tentu banyak organisasi masyarakat sipil yang menolak, salah satunya datang dari organisasi pemberi bantuan hukum.
Publik pun diperkenalkan dengan beberapa aturan yang dianggap janggal dan akan mengganggu kebebasan sipil. Seperti pasal tentang penghinaan terhadap presiden, pasal penghinaan lembaga negara, pasal tentang demonstrasi, dan pasal tentang penyebaran ajaran Marxisme.
Siapa yang menguasai hukum?
Saya tidak akan membedah pasal-pasal atau redaksi dari pasal itu, karena sudah banyak yang mengulasnya. Saya akan mengulik tentang bagaimana kepidanaan justru lahir dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Tentang siapa yang menguasai hukum.
Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri menyebut bahwa ada 274,988 kasus pidana yang terjadi sepanjang 2022. Sementara, kasus pidana yang terjadi pada 2016 hanya 52,539. Dari tahun 2016 hingga 2022, data kasus pidana naik secara signifikan.
Dari sejumlah kasus pidana, pencurian adalah kasus yang sering dijumpai. Tindakan pidana ini memang bisa merugikan orang banyak apapun jenis dan status sosial. Pencurian, entah apapun yang dicuri, mulai dari emas, barang elektronik, atau barang berharga lainya adalah tindakan yang menyebabkan pidana.
Akan tetapi di sinilah ketimpanganya. Pelaku pencurian biasa datang dari kelas bawah yang tidak dapat mengakses pekerjaan layak atau miskin secara struktural. Sementara, pencuri berdasi (istilah untuk koruptor) walaupun dapat dipenjara, tetapi masih bernasib baik dan kadang memperoleh ‘kebebasan’ secara curang.
Saya pernah melihat langsung, bagaimana seseorang dikenakan tuduhan pencurian karena mempertahankan tanahnya dari perampasan lahan oleh korporasi sawit PT Mamuang (anak perusahaan Astra Group). Seorang petani asal Kecamatan Rio Pakava, Donggala, terpaksa merasakan jeruji besi karena dikriminalisasi atau dituduh mencuri sawit milik perusahaan. Padahal sawit itu merupakan miliknya.
Di tempat lain, pada 2015, seorang wanita tua bernama Asyani, divonis bersalah lantaran mencuri kayu milik Perhutani Situbondo.
Dari situ, masyarakat mulai memandang bahwa penegakan hukum di Indonesia timpang. Pasalnya, masyarakat kelas bawah tidak mampu mengakses hukum dan ‘mengisi kantong hakim’. Hal ini disebabkan, karena cara pandang hukum yang timpang.
Sama seperti kebebasan berkespresi atau mengkritik kebijakan negara. Walaupun Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM telah menjelaskan dimana-mana bahwa pasal mengenai hinaan terhadap Presiden dan lembaga negara bukan untuk menghilangkan kritik, akan tetapi bukankah semua pejabat negara adalah kelas sosial yang bernafsu mempertahankan kekuasaanya, dan tidak mau ada gangguan terhadap kekuasaan itu.
Pasal hinaan itu pada akhirnya jadi sebanding dengan pasal tentang pemberitahuan demonstrasi yang dapat menyebabkan kekacauan atau konflik.
Semua itu adalah wujud ekspresi dari kelas yang berkuasa yang mencoba menghegemoni semangat merancang kitab hukum pidana dengan spirit nasionalisme.
Apa pun paradigma dari perubahan akan hukum pidana, yang perlu diketahui—tidak hanya oleh penegak hukum—bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi akan selalu menyebabkan hukum timpang ketika dilaksanakan.
Siapa yang mampu menguasai modal akan menguasai hukum serta pelaksanaannya. Adapun mereka yang tidak menguasai modal akan selalu jadi pesakitan.
Oleh karena itu, bagi saya, alih-alih sekedar memperbaiki hukum pidana warisan kolonial dengan dalih nasionalisme, yang diperlukan ialah merancang sistem ekonomi dan sosial baru.
*) Penulis: Richard Labiro, Dosen Ilmu Administrasi Pemerintahan, FISIP, Untad.
Catatan redaksi: Tutura.Id menerima tulisan berbentuk opini sepanjang 500-800 kata. Tulisan opini merupakan pandangan pribadi dari penulis.