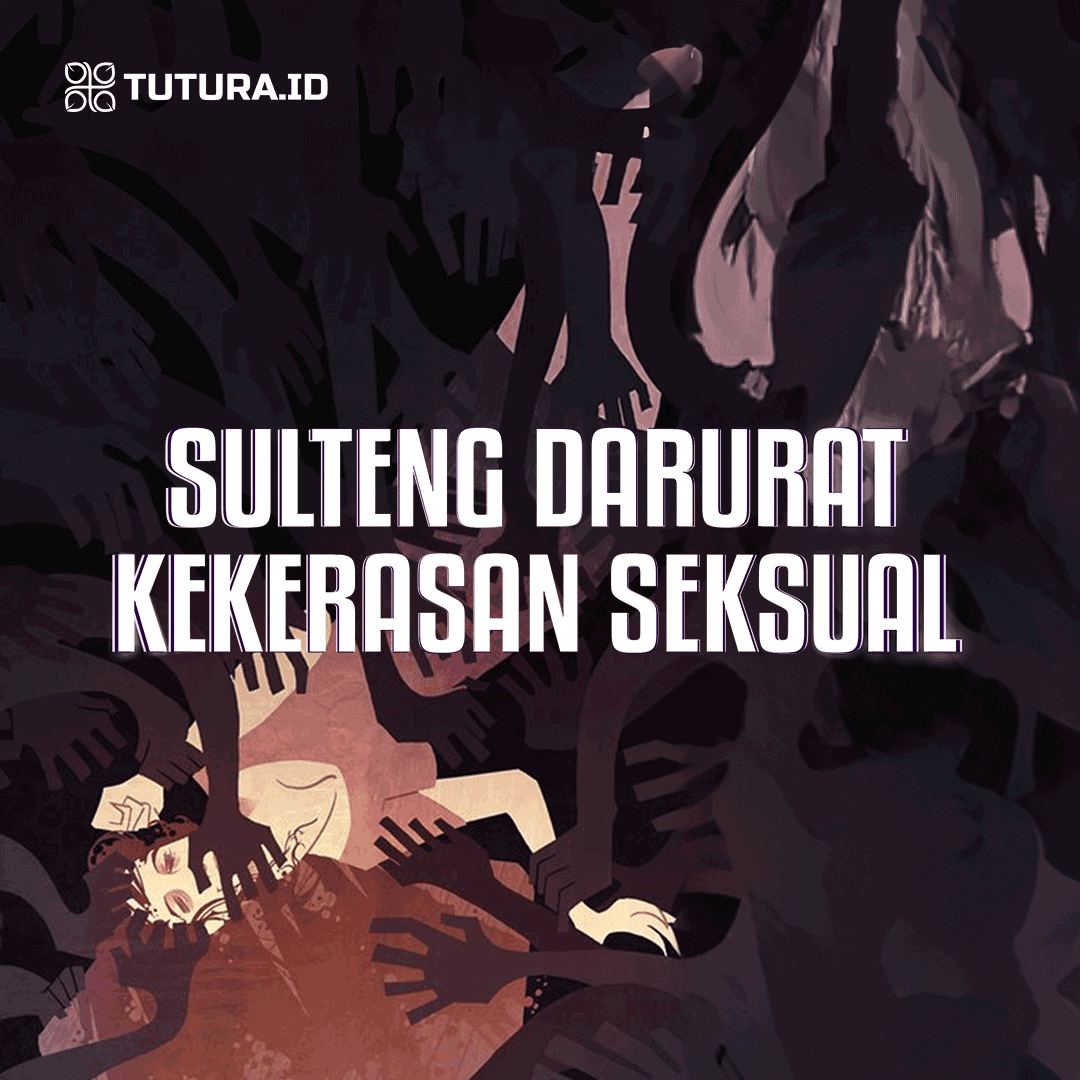Indonesia sedang jadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Acara yang gaungnya sudah dimulai setahun lalu itu dipusatkan di Denpasar, Bali.
Itu merupakan pertemuan tingkat tinggi untuk para kepala negara anggota G20. Mereka bakal bahas tiga topik utama, yakni arsitektur kesehatan global (dampak dari pandemi), transformasi digital, dan transisi energi.
Perkara transisi energi yang jadi fokus utama dalam tulisan ini. Saat ini, kondisi pemanasan global dan perubahan iklim memaksa negara-negara untuk mengatur konsumsi energi. Harapannya, kita bisa memperpanjang umur bumi dengan mengatur konsumsi energi.
Salah satu tujuannya ialah nol emisi karbon (net zero emission). Cara utamanya mengalihkan konsumsi energi, dari "yang kotor" jadi "yang bersih dan berkelanjutan."
G20 tak sekadar punya pertemuan KTT, yang menghadirkan para kepala negara--atau yang mewakili. Lebih dari itu, seperti semangat pembentukan awalnya (pada 1999) untuk merespons situasi ekonomi dunia, maka G20 akan menghadirkan pemangku kepentingan utama bidang ekonomi; mulai dari para menteri keuangan hingga gubernur bank sentral dari negara anggota.
Pada aspek mitigasi perubahan iklim, mereka hendak mengupayakan transformasi konsumsi energi untuk mendonori pembangunan energi baru terbarukan; terutama di negara berkembang macam Indonesia.
Misalnya, KTT G20, mencatat terbentuknya Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform (ETM Platform Indonesia), satu sarana Indonesia untuk jangkau pendanaan dari negara lain di skitar program transisi energi.
Ada pula retorika pendanaan Rp310 triliun dari Just Energy Transition Partnership (JETP), koalisi energi bersih dari sejumlah negara, termasuk AS dan Jepang.
Namun bantuan menciptakan energi bersih atau energi baru terbarukan atau kosakata lain; jadi tak banyak berarti lantaran dibarengi dengan pendanaan kepada perusahaan tambang yang dilakukan bank-bank internasional.

Anomali pendanaan
Bank atau lembaga keuangan internasional kerap menyuntikan dana sedar pada perusahaan pertambangan.
Koalisi organisasi masyarakat sipil global, Forest & Finance menemukan bahwa bank-bank di dunia memberikan USD37,7 miliar kepada 23 perusahaan pertambangan, yang berisiko menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran air, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Dari dana sebesar itu, sejak 2016, usai Perjanjian Iklim Paris diteken, sampai 2021, pembiayaan terbanyak diberikan kepada perusahaan-perusahaan di wilayah tropis Asia Tenggara (USD 16,1 miliar)--Indonesia termasuk di dalamnya.
Padahal, penyebab kerusakan hutan—benteng terakhir lingkungan—banyak yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan tambang.
Di Morowali misalnya, beberapa area dalam kawasan industri nikel besar-besaran itu mengharuskan pembukaan lahan dengan menggusur hutan dan meratakan perbukitan. Majalah Tempo, pada akhir Januari 2022, menyebut angka luasan deforestasi di Sulawesi yang mencapai setengah juta hektare. Penyebab utamanya ialah industri nikel skala besar.
Belum lagi bila membicarakan ketergantungan perusahaan tambang pada pembangkit listrik tenaga batu bara (alias PLTU, tenaga uap)—sumber energi kotor. Ada taksiran kelompok pegiat lingkungan yang menyebut Industri nikel di Sulawesi, punya ketergantungan hingga 80 persen terhadap listrik asupan batu bara.
Padahal batu bara menciptakan emisi. Tumpukan emisi (mudahnya polusi) mengepul di udara, membuat semacam selimut yang membekap bumi. Di sisi lain, Hutan yang bisa jadi pengikat emisi juga menyusut dan bisa melenyap. Alhasil kian lama bumi makin panas dalam selimut polusi ini.
Pemanasan global. Lalu ada perubahan iklim. Bumi makin panas. Cuaca ekstrem kian sering terjadi. Bencana, misalnya, banjir dan tanah longsor jadi kian sering terdengar.
Inilah yang membuat bank sentral dan pendanaan internasional seperti pedang bermata dua. Di satu sisi mereka berusaha untuk memberikan dana hijau berkelanjutan, tetapi mereka ikut bertanggung jawab terhadap deforestasi serta pemanasan global.
Seharusnya G20 dan pertemuan sejenisnya menjadi ajang evaluasi untuk menghentikan pendanaan terhadap pembiayaan energi fosil yang terprivatisasi di perusahaan tambang transnasional.
Perlu mendorong transisi keadilan iklim yang menjadi solusi alternatif dari False Solution G20. Transisi keadilan iklim merupakan platform advokasi masyaraka terdampak perubahan iklim—mereka berisikan kelas buruh, masyarakat miskin kulit berwarna, masyarakat adat, petani dan nelayan.
*) Penulis: Richard Labiro, Dosen Ilmu Administrasi Pemerintahan, FISIP, Untad.
Catatan redaksi: Tutura.Id menerima tulisan berbentuk opini sepanjang 500-800 kata. Tulisan opini merupakan pandangan pribadi dari penulis.
Richard Labiro tutura.id g20 pendanaan bank internasional transisi energi dana bank