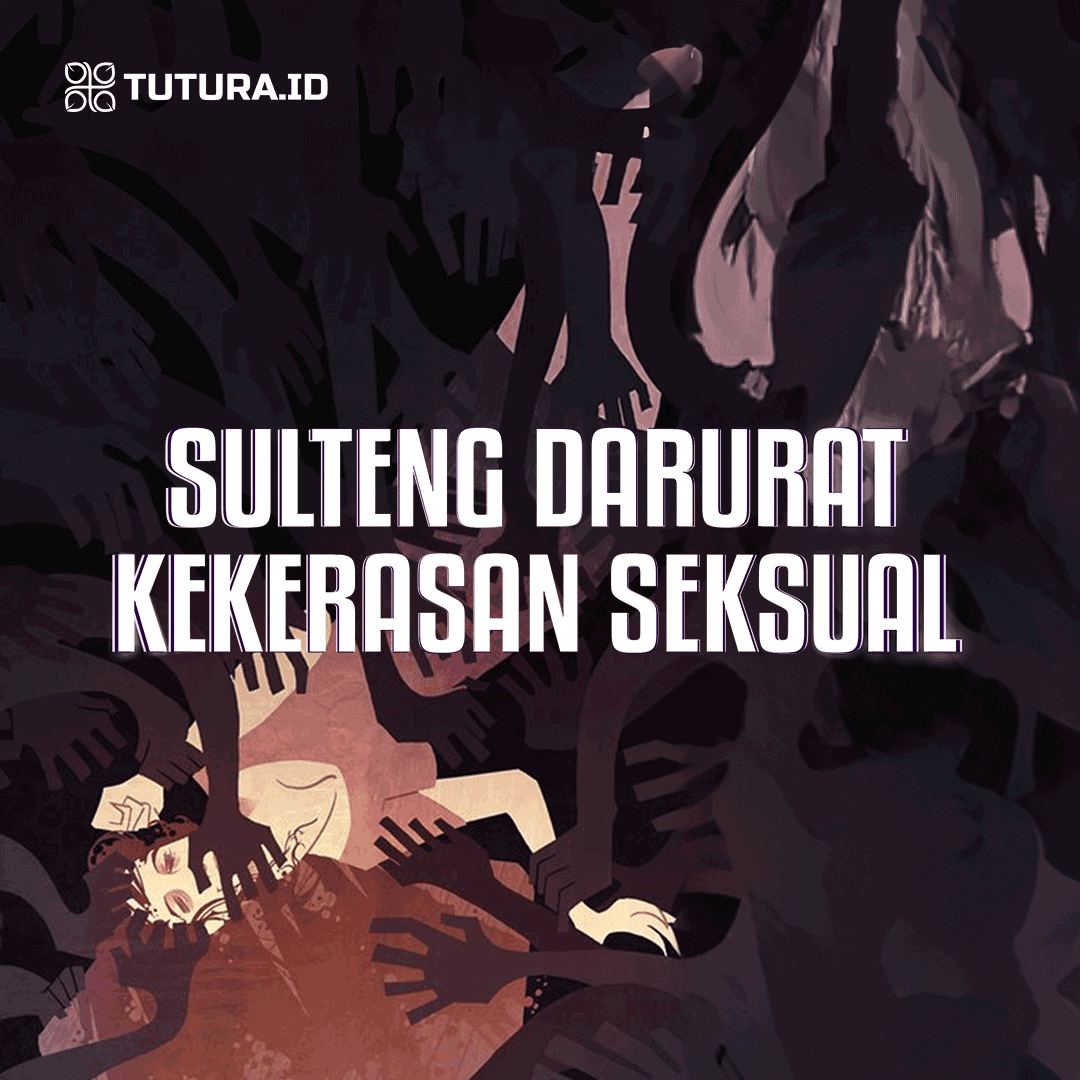Sulawesi Tengah kini tengah menjadi sorotan atas kasus kekerasan seksual. Pagi tadi (9/6/2023), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si mendarat di Kota Palu.
Berdasarkan agenda kunjungan yang diterima Tutura.Id, I Gusti Ayu akan menjenguk anak “R”, yang menjadi korban kekerasan seksual 11 pria di Kabupaten Parigi Moutong. Kunjungan ke RSUD Undata ini disebut menjadi agenda utama sang menteri.
Di luar perhatian yang diberikan oleh unsur pemerintah pusat itu, ditataran lokal Sulawesi Tengah, perhatian terhadap isu kekerasan seksual terus menguat sejak kasus “R” mencuat ke publik. Aksi solidaritas dan ruang-ruang diskusi digelar untuk membicarakan kasus ini.
Salah satunya gelar wicara yang dilakukan secara hybrid pada Rabu (7/6) petang. Ruang diskusi yang diinisiasi oleh Forum Sudutpandang ini dihadiri sejumlah komunitas dan pekerja kreatif di Kota Palu.
Ada empat orang yang tampil sebagai narasumber. Dua di antaranya hadir secara luring di Raego Cafe, Jalan Ki Maja, Besusu Barat, yang jadi tempat diskusi. Mereka adalah Direktur Libu Perempuan Dewi Rana Amir, S.H., M.Si. dan psikolog klinis I Putu Ardika Yana, M.Psi.
Sementara yang bergabung secara daring adalah spesialis forensik dan medikolegal dr. Stephanie Renni Anindita Sp.FM dan Lian Gogali mewakili Institut Mosintuwu.
Diskusi tersebut dibuat khusus untuk menyatakan dukungan dan menciptakan narasi yang berpihak kepada korban kekerasan seksual. Berangkat dari peristiwa dari menimpa korban anak “R”.
Maksud ini dapat ditangkap dengan jelas dari tagline yang diusung, yakni “Berpihak pada Korban, Bersuara untuk Keadilan” dengan tagar #sultengdaruratkekerasanseksual.
Sepanjang gelar wicara berlangsung, keempat narasumber memberikan kesaksian mereka selama menjadi pendamping korban kekerasan seksual.
Alhasil peserta diskusi jadi makin tahu situasi dan tantangan yang dihadapi oleh korban kekerasan tidaklah mudah. Olehnya keberpihakan terhadap korban menjadi wajib.

Tetap kawal kasus sebagai pemerkosaan
Dewi Rana Amir selaku praktisi hukum yang tergabung dalam tim pendamping korban anak “R”, mengungkapkan Sulteng sedang tidak baik-baik saja terkait kekerasan seksual.
Libu Perempuan, ujar Dewi, telah menangani 39 kasus hingga Mei 2023. Korban paling banyak adalah anak perempuan. Jadi, “R” bukanlah satu-satunya.
Serangkaian kasus kekerasan seksual terjadi lantaran faktor ekonomi, relasi kuasa, dan regulasi yang kerap tidak mengawal dengan baik pengalaman hidup perempuan dalam penerapan pasal-pasal hukum. Padahal penyerangan terhadap unsur reproduksi tidak bisa dipisahkan dari tubuh perempuan.
“Ketika bicara soal hukum, Anda tidak bisa meninggalkan pengalaman-pengalaman ini. Anda harus membawa pengalaman itu ke dalam konteks hukum dan itu yang kita sebut dengan perspektif keadilan tubuh perempuan atau korban. Dan ini (kasus anak “R”, red), menurut saya harus terus didorong,” ujarnya.
Dewi mencontohkan seorang korban kekerasan seksual yang bahkan setelah menikah tetap tidak bisa membuka lebar kakinya. Ada trauma yang sangat membekas di sana.
Oleh karena itu, koneksi aturan satu dengan yang lain harus dikaitkan dengan melihat konteks korban. Jangan sampai korban anak “R” yang kini sedang dalam proses pemulihan dibiaskan oleh perspektif lain tanpa melihat bagaimana organ reproduksi “R” diserang.
Di akhir kesaksiannya, Dewi Rana menegaskan dirinya akan tetap mengawal kasus “R” agar digolongkan sebagai tindakan pemerkosaan, karena tidak ingin memisahkan pengalaman korban.
“Jangan melepaskan advokasi ini dari pengalaman tubuh perempuan, yang seharusnya ikut dibawa dalam skema advokasi dan harus tetap menyuarakan ini di luar,” tegasnya.
Dia pun mengingatkan bahwa kasus kekerasan seksual tidak bisa hanya dilihat dari kasus kekerasan fisik, namun seluruh proses, dari awal hingga terjadinya. Misalnya, adanya bentuk iming-iming atau bujuk rayu yang dilontarkan pada korban, juga harus dilihat.
Pasalnya, bila hanya melihat unsur kekerasan secara fisik, tanpa melihatnya secara utuh, maka dia khawatir kasus serupa di masa depan, tidak diproses dengan baik di pengadilan. Itu bisa saja terjadi karena menghilangkan unsur-unsur kekerasan nonfisik.

Bukti yang memudar
Sementara itu, Spesialis Forensik dan Medikolegal, dr. Stephanie Renni Anindita Sp.FM, menitikberatkan pada pembuktian kekerasan seksual di mata hukum.
Berdasarkan pengalamannya, biasanya korban kekerasan seksual enggan langsung melapor. Ketika keberanian untuk melapor sudah muncul, bukti terlanjur memudar. Tidak lagi kuat menyeret pelaku ke dalam bui.
Dia mencontohkan ada anak perempuan berhubungan dengan pria berkeluarga. Keduanya melakukan seks hampir setahun. Pada saat kasus tersebut terlapor, bukti adanya terjadi persetubuhan atau kekerasan seksual sudah hilang.
Meski ada pembelaan yang mengatakan seks dilakukan suka sama suka, namun Stephanie menegaskan seks yang terjadi merupakan bentuk kekerasan seksual. Sebab pihak perempuan adalah seorang anak di bawah umur dan laki-lakinya adalah seorang pria dewasa. Ada relasi kuasa dan pengaruh yang kuat.
Berdasarkan pengalamannya, 90 persen pihak forensik tidak pernah menemukan tanda kekerasan dalam persetubuhan, dikarenakan jeda waktu yang lama dari kejadian dan saat korban melapor. Olehnya, strategi terbaik saat ini adalah banyak mengedukasi orang agar tidak terjadi kekerasan seksual.
“Sampai saat ini saya sebagai dokter forensik cuma bisa berusaha untuk mencegah saja dengan mengedukasi. Dari kasus yang saya tangani, saya hanya bisa mencegah. Karena pada saat sudah terjadi perlindungan hukum bagi korban, sebagai gambaran dari 100 kasus, 90 persen atau lebih itu akan susah untuk bisa mencapai keadilan,” ungkapnya.
Stephanie pun mengaku merasa sangat susah menangani kasus kekerasan seksual ketika korbannya sudah dewasa. Sangat susah diseret ke pengadilan. Apalagi tanpa adanya bukti kekerasan seksual secara fisik.
“Saya pernah menjadi saksi ahli di pengadilan dan saya melihat bagaimana korbannya ini mendapatkan trauma berkali-kali di pengadilan. Apalagi saat saya membacakan hasil visum, di mana saya membacakan hasil yang saya dapatkan. Di situ hanya bisa menjelaskan pernah ada kejadian persetubuhan pada alat kelamin, tetapi saya tidak bisa menemukan adanya kekerasan,” sambungnya.
Kepada peserta gelar wicara yang hadir secara daring dan luring, Stephanie menegaskan pentingnya mengedukasi orang lain dan melindungi korban kekerasan seksual. Sebab, kekerasan seksual yang dialami korban bukan hanya sekadar fisik, tapi juga trauma secara psikis.

Karakteristik mental pelaku
Kesaksian ketiga diceritakan I Putu Ardika Yana, M.Psi. selaku psikolog klinis dan pendamping psikolog bagi korban anak “R”. Sepanjang pengalamannya mendampingi korban lain dengan kasus serupa, Putu mengatakan bahwa pembuktian terkait kasus kekerasan seksual merupakan sesuatu yang susah-susah gampang.
Namun, beberapa waktu terakhir ia merasa sangat positif dalam persidangan. Pasalnya beberapa hakim dan jaksa sudah lebih mengerti bahwa pemeriksaan psikolog klinis merupakan salah satu bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Saya senangnya dalam banyak case ,terutama di tahun 2022, hampir semua kasus yang kami tangani hanya dengan alat bukti visum, terus kemudian saksi, dan keterangan psikolog klinis itu menghasilkan hukuman di atas 10 tahun,” ceritanya.
Putu mengatakan ada yang sulit untuk dimasuki lebih jauh terkait pemahaman masyarakat mengenai aspek kekerasan seksual. Terlebih lagi ketika pemahaman religius diartikan sangat keras menyangkut perilaku manusia.
Karena menurutnya, dalam konteks kekerasan seksual tidak bisa dinilai dengan hitam atau putih. Ada banyaknya dinamika yang terjadi sebagai penyebab.
Dia mencontohkan jika seorang anak di bawah umur datang "menjual diri" kepada orang dewasa dengan alasan butuh uang, tawaran itu seharusnya tidak diiyakan. Ada solusi lain agar anak tersebut bisa mendapatkan uang. Artinya pemahaman berkaitan dengan emosi dan kematangan seseorang dalam menghadapi suatu masalah jadi penting.
Putu juga menyinggung pentingnya memetakan karakteristik mental para pelaku. Hal ini berkaitan dalam upaya menyusun program pencegahan kekerasan seksual.
“Karena kalau kita punya pola yang jelas mengenai karakteristik pribadi dari pelaku kekerasan, kita bisa menentukan paling tidak ‘blueprint’ untuk pencegahan. Saat ini ranah pencegahan kita kalau bukan sama anak, ya, sama perempuan. Sementara pelakunya adalah laki-laki. Lalu bagaimana laki-laki ini menjadi bagian dari part of pencegahan? Makanya penting menurut saya untuk memahami kondisi psikisnya mereka,” sambungnya.
Hal lain yang tak kalah penting menurut Putu adalah penanganan psikologis kepada korban. Bukan hanya fokus pada penanganan fisik dan memenjarakan tersangka. Olehnya, ia meminta kepada masyarakat agar tetap menaruh perhatian terhadap kasus kekerasan seksual anak “R”. Dengan begitu korban merasa tidak berjalan sendiri.

Fenomena gang rape
Lian Gogali dari Institut Mosintuwu membuka ceritanya dengan menyodorkan serangkaian data peristiwa gang rape alias pemerkosaan beramai-ramai dengan korban anak di Sulteng. Mulai dari Tahun 2022 hingga Mei 2023.
Dia menyebut pemerkosaan beramai-ramai oleh 10 orang pemuda kepada 1 siswi SMP di Bangkep sebagai kasus gang rape pertama yang disodorkannya. Disusul pemerkosaan 1 siswi SMP di Tojo Unauna oleh 13 pemuda.
Adapula kasus pelajar SMK Tojo Una-Una yang diperkosa pejabat pengadilan agama dan pemerkosaan anak 12 tahun di Kabupaten Sigi.
“Kalau misalnya melihat dari para pelaku kekerasan seksual ini, saya bisa menyebutkan bahwa sebagian besar, sayangnya, dilakukan pejabat negeri. Misalnya kita balik tahun 2021, ada Kapolsek Parigi yang memerkosa perempuan berusia 21 tahun. Kemudian Juni 2022, pejabat Pengadilan Agama Tojo Una-Una melakukan pemerkosaan, kemudian Maret pada 2023 perempuan diperkosa lalu dibunuh yang pelakunya anggota TNI, kemudian perwira polisi berpangkat Ipda pada bulan Mei 2023 anak usia 15 tahun di Parigi Moutong,” ungkapnya.
Dari serangkaian kekerasan, yang dibeberkan olehnya, Lian mengakui bila tidak salah bila Sulawesi Tengah sedang dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Olehnya, dibutuhkan upaya sinergis untuk saling menguatkan dan mematahkan lingkar kekerasan pada perempuan dan anak.
Lian menjelaskan dari data yang ada pada Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) Institut Mosintuwu di Tahun 2021 dan 2022, mengungkapkan korban dan pelaku kekerasan seksual di Kabupaten Poso mememiliki hubungan yang dekat. Misalnya hubungan keluarga, tetangga, hingga orang dalam satu kampung.
Selain hubungan yang dekat, Lian mengungkapkan kekerasan seksual juga terjadi dalam konteks relasi kuasa yang kuat. Tidak sedikit pelaku adalah pejabat publik. Ini pun menjadi tantangan dalam upaya mematahkan lingkar kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Pasalnya, Lian mempertanyakan jika setingkat pejabat publik belum memahami undang-undang kekerasan seksual. Padahal seharusnya merekalah yang melindungi korban bukan malah menjadi penyebab kekerasan seksual.
“Dalam konteks ini, kami (Institut Mosintuvu, red) merasa yang paling penting dimasifkan adalah gerakan perlindungan perempuan dan anak dalam lingkar komunitas. Ini latar belakangnya sebenarnya selain karena banyaknya kasus, tapi juga karena lembaga penyedia layanan sangat terbatas. Tidak bisa menjangkau desa-desa terpencil. Semantera masih banyak orang berpikir kalau ke polisi itu lama prosesnya. Memakan waktu, konsekuensinya mengeluarkan biaya,” paparnya.
Lian juga menggarisbawahi upaya pencegahan bisa dilakukan dengan cara mengaktifkan komunitas. Karena kekerasan seksual muncul dari hubungan dekat, maka solusi perlindungan juga bisa muncul dari hubungan ini.
Dia mengatakan lingkar perlindungan terhadap kekerasan seksual bisa dibangun dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan menyebar kepada lingkungan tetangga, lingkungan sekolah, hingga lingkungan tempat kerja.
pemerkosaan kekerasan seksual pemerkosaan anak kasus kekerasan Sulteng Kota Palu Sulteng Kabupaten Parimo Kabupaten Poso Tojo Unauna Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak