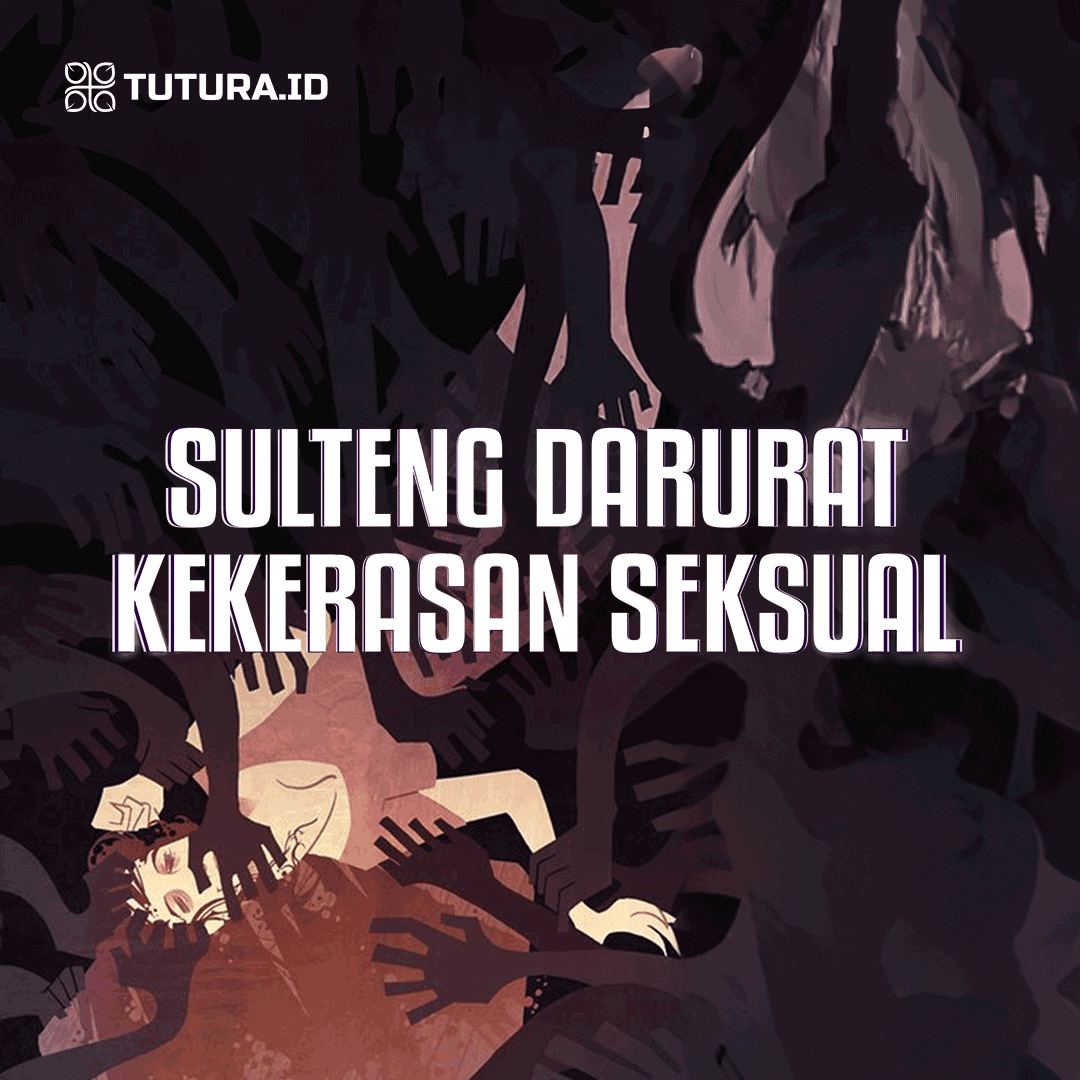Jarum jam telah menunjukkan pukul 20.42 WITA ketika saya menyambangi Perguruan Barongsai Tiga Naga di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Tondo (20/1/2023).
Saat memarkir kendaraan di depan sebuah jejeran ruko, tampak delapan pemuda giat berlatih di tanah lapang yang diapit oleh dua bangunan ruko. Gerakan akrobatik khas barongsai mereka praktikkan dengan gesit.
Terkadang mereka saling tegur. Mengingatkan teknik yang benar dalam barongsai. Maklum beberapa orang yang ikut latihan masih tergolong pendatang baru. Alhasil beberapa kali bikin gerakan yang salah.
Sesekali mereka ambil jeda demi menstabilkan kembali tarikan napas, membasuh peluh yang membasahi badan, dan mengebulkan asap rokok dari mulut. Mencoba rileks. Tawa lepas pun terdengar dari para pemain yang masih muda ini.
Latihan yang mereka lakukan kali ini merupakan persiapan untuk pertunjukan yang digelar menjelang perayaan Imlek.
“Tunggu dulu ee, suhu (guru, red.) masih ada tamu,” ujar salah satu pemain barongsai kepada saya. Sembari menunggu, saya pun lanjut menyaksikan mereka kembali menyambung sesi latihan.
Sekira 30 menit menunggu, akhirnya saya dipersilakan masuk ke dalam ruko menemui suhu Perguruan Barongsai Tiga Naga.
Arifuddin, 49 tahun, suhu yang dimaksud, datang menyambut dan mempersilakan saya duduk. Mengenakan jubah berwarna putih, Arif—demikian sapaan akrabnya—berperawakan tegap. Cukurannya klimis.
“Perguruan ini berdiri sejak 2007. Waktu itu namanya masih Barongsai Karuna Dipa. Sekitar lima tahun berikutnya diubah menjadi Barongsai Tiga Naga. Itu mengartikan tiga unsur kekuatan,” jelas Arif.
Wajar jika namanya perguruan alih-alih sanggar yang biasanya lekat untuk tempat belajar menari. Pasalnya barongsai, yang juga bertumpu pada olah tubuh para penarinya, kerap memadukan geraknya dengan bela diri atau aksi akrobatik. Oleh karena itu, orang-orang kerap menyebutnya atraksi ketimbang tari.
Arif mengenangkan awal ketertarikannya menggeluti kesenian barongsai. Kala itu ia masih berstatus pelajar kelas tiga sekolah menengah pertama. Dengan segala keterbatasan, mulai dari pelarangan oleh pemerintah Orde Baru hingga ketiadaan guru yang mengajari, Arif nekat belajar secara autodidak.
“Saya belajar terus dengan tekun. Akhirnya tahun 1989 saya sempat masuk salah satu vihara. Dipercayakan juga bergabung dalam tim barongsai. Waktu itu pelatihnya langsung dari Negeri Tiongkok,” ungkap Arif.
Melompat beberapa dekade kemudian, Arif masygul kala menyambangi Vihara Karuna Dipa, medio September 2006. Beberapa anak muda yang antusias mendalami barongsai terpaksa belajar sendiri karena lagi-lagi tidak punya mentor mumpuni.
“Pernah ada yang melatih dari Jawa, tapi saya tidak tahu persis kenapa berhenti. Mungkin karena anggaran atau jarak yang terlalu jauh. Padahal untuk melatih anak-anak agar cakap bukan hanya butuh waktu sehari, seminggu, atau sebulan, tapi harus bertahun-tahun,” demikian Arif menjelaskan.
Bermaksud memperbaiki kondisi tersebut, terketuklah Arif membuka Perguruan Barongsai Karuna Dipa yang kini bersalin nama jadi Perguruan Barongsai Tiga Naga.
Hal menarik dalam perguruan barongsai yang diasuhnya adalah terbukanya kesempatan belajar untuk semua. Murid-muridnya tak melulu bertalian darah Tionghoa. Ada yang dari Suku Kaili, Jawa, Flores, bahkan Arif berasal dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan.
Kebinekaan tadi menciptakan toleransi di Perguruan Barongsai Tiga Naga. Lagi pula, barongsai sebagai kesenian seharusnya memang untuk dipelajari semua orang tanpa ada sekat golongan tertentu.
.jpg)
Sejarah barongsai dan awal kehadirannya di tanah air
Termaktub dalam buku The Dramatic Oeuvre of Chu Yu-Tun (1379–1439), saat Dinasti Tang berkuasa (618-907 Masehi), singa yang sebelumnya hewan asing di daratan Tiongkok saat itu telah menjadi bentuk hiburan budaya yang khas. Acara-acara di istana kekaisaran telah pula sering mengundang kehadiran penari barongsai untuk menghibur tetamu.
Pun demikian, beberapa literatur lain menyebut bahwa kemungkinan tarian barongsai sudah dikenal warga Tionghoa sejak awal abad ke-3 Masehi ketika masa pemerintahan Dinasti Qin.
Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, singa perlambang keberanian, kekuatan, kebijakan, dan keunggulan. Sementara sebagai tarian, barongsai dimaksudkan mengusir roh jahat/energi negatif, mendatangkan kemakmuran, dan pembawa keberuntungan.
Barongsai mencapai kepopulerannya sebagai kesenian tradisional Tiongkok pada zaman dinasti Selatan-Utara (Nan Bei) tahun 420-589 Masehi.
Nun jauh di negeri asalnya, tidak dikenal istilah barongsai. Lidah warga Tiongkok menyebutnya Wu Shi atau Lion Dance dalam konteks internasional. Penamaan barongsai merupakan bukti akulturasi budaya.
“Secara bahasa, kata barongsai merupakan gabungan dari “barong” yang berasal dari Bahasa Jawa dan kata “sai” dari dialek Hokkian yang artinya singa,” jelas Irwan Abdullah, Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Barong atau barongan merupakan figur dalam mitologi Jawa dan Bali yang digambarkan dalam bentuk samaran seperti binatang. Biasanya merujuk pada singa.
Jenis singa dalam barongsai ada dua. Jenis pertama singa utara yang memiliki surai ikal dan berkaki empat. Sementara yang kedua singa selatan. Tampilan fisiknya bersisik dilengkapi tanduk. Jumlah kaki bervariasi antara dua atau empat.
Perjalanan barongsai melintasi berbagai benua seturut diaspora para warganya yang mencari pengharapan di tempat tinggal baru. Para ahli sejarah menduga barongsai mendarat di tanah air sekitar abad ke-17. Periode ketika migrasi besar warga Tiongkok Selatan terjadi melalui jalur perdagangan.
Barongsai makin populer di Nusantara seturut kehadiran Tiong Hoa Hwe Koan alias Rumah Perkumpulan Tionghoa, organisasi yang berdiri pada 17 Maret 1900 di Batavia (kini Jakarta). Perkumpulan itu ingin mendorong para warga etnis Tionghoa yang bermukim di Hindia Belanda untuk melestarikan kebudayaan nenek moyang. Wujud dari ikhtiar itu akhirnya bikin barongsai jadi makin dikenali awam.
Jika awalnya dikenal sebagai tari ritual sakral yang dilakukan pada waktu tertentu dan untuk tujuan khusus, barongsai lama-kelamaan berkembang jadi kesenian publik. Hampir dalam setiap penampilan barongsai selalu ramai oleh penonton. Penggemarnya banyak.
Sejarah perjalanan bangsa kita mencatat periode ketika barongsai terpasung setelah meletusnya Gerakan 30 September. Bentuk konkretnya melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.
Inpres tersebut menitahkan segala kegiatan kultural yang berpusat pada negeri leluhur warga Tionghoa harus dilakukan secara internal dalam hubungan keluarga atau perorangan. Segala bentuk perayaan pesta agama dan adat istiadat Tionghoa juga harus dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga.
Setelah masa reformasi yang mengakhiri periode kekuasaan Orde Baru, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut inpres tadi. Barongsai kembali hadir di depan khalayak ramai tanpa harus sembunyi di balik tembok kelenteng atau vihara saat perayaan Imlek.
Bahkan kini barongsai juga bisa hadir di berbagai ruang publik seperti atrium mal sebagai seni pertunjukan nan menghibur. Telah berkembang pula menjadi cabang olahraga yang diakui Komite Olahraga Nasional Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2010 turut pula menetapkan barongsai sebagai salah satu warisan budaya takbenda Indonesia.
Selama menggeluti kesenian barongsai bersama perguruannya, Arif mengaku tak pernah mendapatkan cemoohan dari masyarakat.
Justru menurut Iqbal (22) dan Ipung (26), salah dua orang yang belajar barongsai di perguruan tersebut, selama ini mereka menuai respons sebaliknya. “Malahan apresiasi yang kami dapatkan. Mungkin karena kami bukan orang keturunan Tionghoa yang bermain,” kata mereka.
barongsai wu shi lion dance sejarah diaspora Perguruan Barongsai Tiga Naga Tionghoa Tiongkok kesenian budaya tarian vihara kelenteng Karuna Dipa Imlek