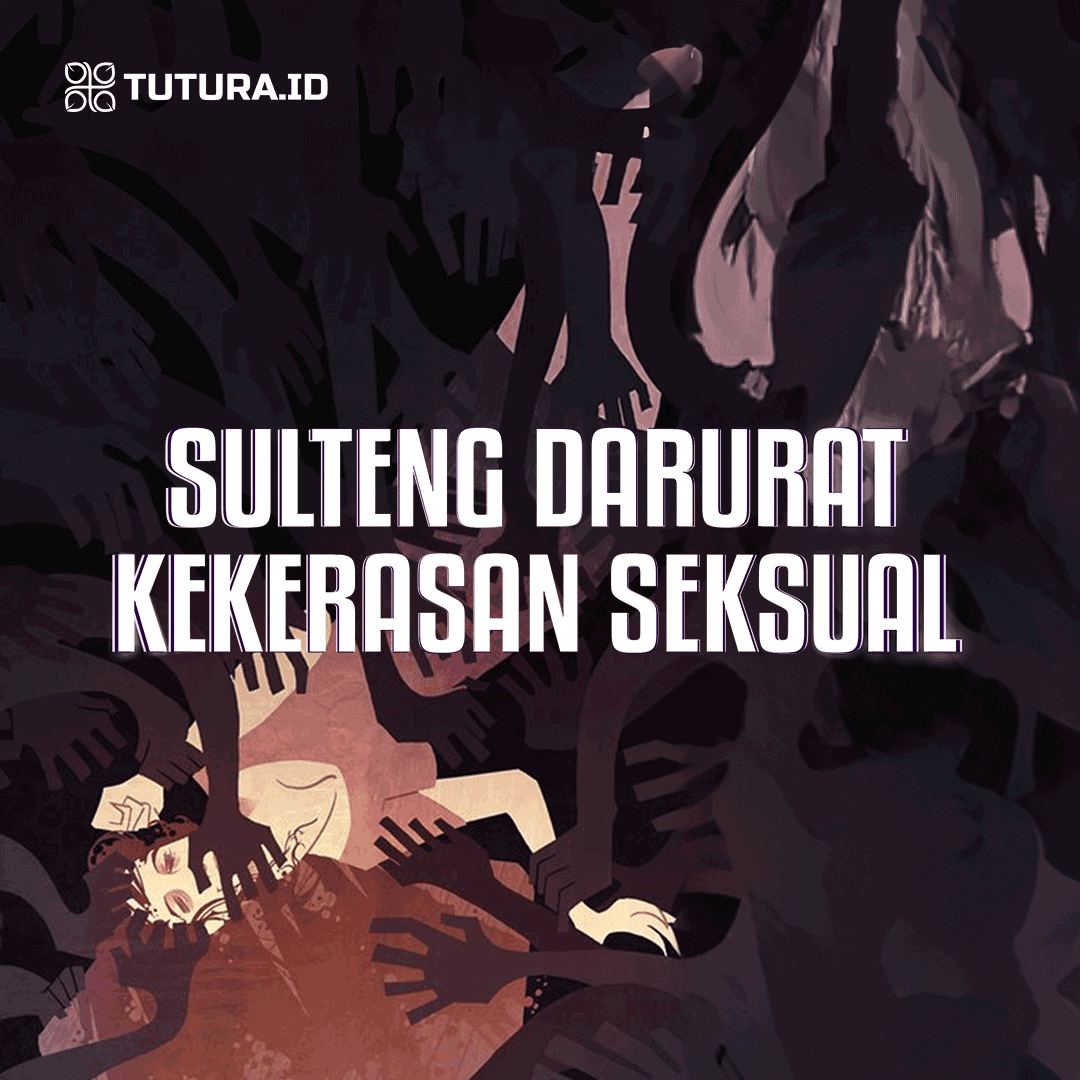Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Hunian Sementara (Huntara), Terminal Mamboro, Palu, berakhir damai lewat mekanisme restorative justice. Penyelesaian kasus ini berlangsung di Ruang Keadilan Restoratif Polresta Palu, pada Rabu, 5 April 2023.
Alhasi tersangka A (46), yang sempat ditahan lantaran perbuatan cabulnya, lolos dari jerat hukum. Kasat Reskrim Polresta Palu, Ferdinand Numberi membeberkan bentuk pelecehan yang dilakukan A terhadap korban NP (21).
Mula-mula, A melempar bujuk rayu pada NP. A lantas berusaha mencium pipi, dan bibir, serta memegang payudara NP. Lantaran peristiwa tersebut, NP melapor ke Polresta Palu. Sebelum berlanjut di kepolisian, kasus ini sempat pula disidangkan oleh lembaga adat di Kelurahan Mamboro.
Adapun restorative justice merupakan metode penyelesaian yang didesain untuk menghasilkan resolusi demi memperbaiki keadaan atau kerugian yang ditimbulkan. Dalam restorative justice, pemidanaan diubah menjadi proses mediasi antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya.
Namun, model penyelesaian restorative justice dalam kasus kekerasan seksual ini bersambut kritik dari para pegiat isu perempuan.
Direktur LiBu Perempuan, Dewi Rana Amir meragukan klaim yang menyebut bahwa korban menginginkan perdamaian.
“Pasti ada pertimbangan-pertimbangan besar yang dia (korban) harus deal dengan itu, sehingga mencabut laporannya. Kita menyayangkan hal-hal seperti terjadi," ujarnya saat dihubungi Tutura.Id, Minggu sore (9/4/2023).

Kenapa restorative justice tak cukup?
Dewi menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual akan berdampak pada psikologis korban. Trauma atas peristiwa kekerasan seksual bakal membayangi hari-hari korban. Restorative justice, dalam kacamata Dewi, tidak mempertimbangkan dampak psikologis tersebut.
“Sebetulnya harus mempertimbangkan pemulihan mental dan psikologis korban. Itu bukan sesuatu yang sembuh tiba tiba," ujar tokoh yang sudah lebih dari dua dekade menekuni isu perempuan ini.
Menurut Dewi, upaya mempertemukan korban dan pelaku saja sudah bisa memicu trauma. Konstruksi budaya pun kerap kali menyudutkan korban. Misalnya, tak sedikit orang yang menyalahkan korban pemerkosaan lantaran baju yang dikenakan. Alhasil korban mendapat stigma, dan pelaku cenderung aman.
Situasi budaya macam itu bisa membuka peluang bagi pelaku untuk memanipulasi korban, menggalang dukungan sosial, dan menghindari jerat hukum. Korban bisa disudutkan dan dipaksa untuk menerima kekerasan seksual yang dialaminya. Pada titik ini, korban pun diperhadapkan dengan tekanan berlapis.
Merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kasus kekerasan seksual juga tak bisa diselesaikan dengan mekanisme di luar pengadilan--termasuk restorative justice.
“Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang,” begitu kutipan Pasal 23 UU TPKS.
Pasal 22 UU TPKS juga telah mengatur agar penyidik (kepolisian) wajib melakukan pemeriksaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, dan tanpa intimidasi. Pun diterangkan, penyidik tidak boleh melakukan viktimisasi atas cara hidup, dan kesusilaan.
Dewi pun menyebut bahwa kepolisian harus lebih memahami spirit UU TPKS. Penanganan kasus kekerasan seksual, kata Dewi, memang berbeda dengan kasus lainnya. Bila kasus lain berorientasi pada menghukum pelaku, maka kasus kekerasan seksual berfokus pada keadilan untuk korban.
“Harusnya (kasus di Huntara Mamboro) ini bisa diteruskan (proses hukum). Namun tiba-tiba korban menarik laporan dan tidak dilanjutkan. Di saat yang sama tidak memberikan efek jera bagi pelaku kalau seperti itu," ujar Dewi.
kekerasan seksual huntara huntara mamboro polisi uu tpks perempuan dewi rana amir