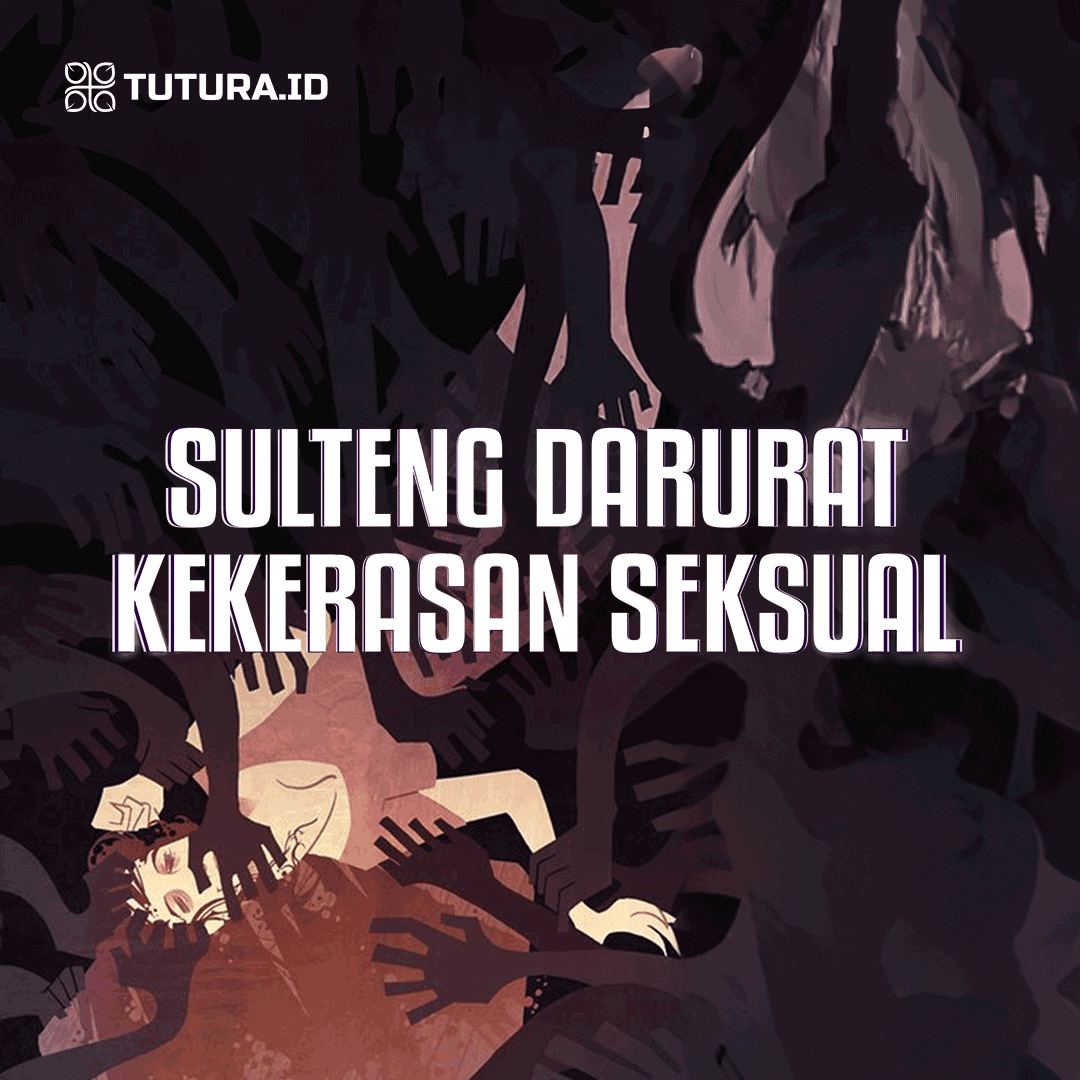Jauh sebelum kita mengenal adanya apotek dan rumah sakit, para tetua mempercayakan pemeliharaan kesehatan dan kebugarannya dengan rutin minum jamu.
Sekadar menghalau masuk angin, pilek, batuk ringan, pegal-pegal, melancarkan haid, hingga perkara meningkatkan stamina cukup dengan minum jamu. Penjualnya biasa datang menyambangi kompleks perumahan dan area keramaian warga saban pagi atau sore.
Paling klasik tentu saja penjual jamu gendong. Istilah ini hadir untuk menyebut model berjualan dengan menggendong bakul berisi aneka botol ramuan jamu yang terbuat mulai dari beras kencur, brotowali, kunyit asam, jahe, sirih, dan temulawak.
Walau kini pemandangan mbok-mbok alias ibu-ibu yang berjualan jamu gendong makin langka tertangkap pandangan, tak membuat langkah Sulami terhenti. Ia dan beberapa kawan seprofesinya masih tetap bertahan menjual jamu dengan cara tradisional ini.
Bagi Sulami, berjualan jamu gendong di Kota Palu sudah dilakoninya selama 40 tahun. Saat kami temui di Pasar Inpres Manonda, Balaroa, Palu Barat, Rabu (23/8/2023) pagi, perempuan berusia 63 ini mengenakan baju panjang merah bermotif dengan bawahan kain batik.
Satu ember plastik ukuran kecil berwarna biru ia tenteng di tangan kirinya. Ember berisi air itu untuk mencuci gelas. Sementara tak ketinggalan caping nyantol di kepala untuk menghalau terik.
Sulami biasanya sudah mengitari Pasar Inpres sejak pukul 07.00-10.00 WITA. Lantaran tinggal di Kalikoa, Kelurahan Ujuna, yang jaraknya lumayan jauh dari pasar jika harus berjalan kaki sambil menggendong bakul berisi botol-botol jamu, Sulami harus naik ojek terlebih dahulu.
Harga jamu per gelas ia banderol mulai dari Rp5000 hingga Rp7000. Pun demikian tak setiap hari ia bisa pulang dengan kondisi semua botol jamunya tandas. Kalau sudah demikian, terpaksa racikan jamu yang tersisa tadi harus ia buang.
Sulami bertahan sebagai pedagang jamu gendong karena tidak bisa menggunakan sepeda dan motor.
“Anakku sebenarnya sudah larang saya jualan. Tapi kalau cuma di rumah saya tidak ba apa-apa. Palingan saya cuma nonton sama tidur. Bosan,” katanya sambil menuangkan segelas jamu kepada pembeli.
Pernah sekali waktu Sulami gantung bakul. Coba berjualan jamu di rumah saja alias menunggu bola. Langkah itu tak dilanjutkannya lantaran sepi pembeli. Ternyata tetap harus jemput bola alias kembali berjualan di pasar lagi.

Sosok yang juga tak jemu berjualan jamu adalah Tukinem (39). Bedanya ia berjualan sambil mengendarai motor bebek. Ada tambahan boks dari kayu di sisi kiri dan kanan motor yang melintang di atas sadel sebagai pengganti bakul. Di dalamnya terdapat botol-botol jamu dengan termos kecil.
Selama 20 tahun berjualan jamu, Tukinem mengaku tak pernah menjajal sebagai penjual jamu gendong. Ia langsung memulainya menggunakan sepeda. Agar bisa menjangkau area lebih jauh dan luas, ibu dua anak ini beralih memanfaatkan moda motor sejak 2010.
Biasanya Tukinem berjualan mulai pukul 07.00 hingga 12.00. Prei sebentar untuk istirahat dan makan siang, ia tarik gas lagi pukul 14.00 sampai menjelang azan maghrib.
Ia biasa menjajakan jamunya dari Pasar Inpres Manonda, bablas ke bagian atas di Jalan Kedondong, melipir Jalan Asam di Kelurahan Lere, hingga memasuki wilayah Kabonena. “Pokoknya muter-muter,” ujarnya ramah kepada Tutura.Id (23/8).
Kelebihan berjualan jamu menggunakan motor juga memungkinkannya mengangkut lebih banyak botol dan produk. Tukinem tak hanya menjual jamu dengan takaran per gelas yang harganya Rp5000, tapi juga menjual jamu dalam kemasan botol plastik. Harganya bervariasi mulai Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.
Adalagi Bu Ngat, demikian panggilannya, yang terus merawat warisan Nusantara ini dengan cara berjualan naik sepeda. Rute jualannya dahulu berkeliling di Jalan Juanda, Teluk Tomini, Tanjung Tururuka, Kartini, Gunung Loli, dan sekitarnya.
Sembari tetap mengayuh sepedanya, Bu Ngat juga melayani pembelian jamu kemasan botol dengan cara memesan via Instagram dan WhatsApp. Harga yang ditawarkan mulai Rp50 ribu (ukuran 1500 mililiter) dan Rp25 ribu (600 mililiter).
Beragam olahan jamu disiapkan Bu Ngat untuk para konsumen, mulai dari kunyit asem, kunyit putih, beras kencur, daun sirih, temulawak, temu ireng, sambiloto, sari rapet, hingga jamu sesuai pesanan.
Makin sedikitnya jumlah pedagang jamu gendong—atau yang memakai kendaraan—di area perkotaan bisa jadi imbas perkembangan zaman. Tambah lagi citra jamu sebagai minuman khas orang tua.
Jarang anak muda yang tertarik mengonsumsi minuman obat tradisional ini. Beberapa cara untuk tidak memutus kebiasaan yang sudah berlangsung ratusan tahun ini adalah dengan mengemas jamu dalam wadah kekinian. Pun menghadirkannya di kafe atau kedai yang jadi tempat-tempat menongkrong favorit remaja era kiwari.
Di Jakarta, misalnya, telah hadir Kafe Acaraki, Kedai Suwe Ora Jamu, dan Jamuwell Café. Sejauh penulusuran kami, konsep menghadirkan kafe dengan menu utama aneka ramuan jamu belum jua hadir di Palu.
View this post on Instagram
Khazanah peninggalan leluhur
Kosa kata “jamu” dalam Bahasa Indonesia adalah serapan dari istilah “jampi” atau “jampyan” dalam Bahasa Jawa Kuno yang berarti obat, pengobatan, dan penawar.
Salah satu varian dari kata tersebut yang hingga sekarang juga langgeng digunakan adalah “husadha”. Artinya tempat orang meminta atau mencari obat. Biasanya dijadikan nama apotek, klinik, bahkan rumah sakit.
Ada banyak kakawin dan kidung peninggalan dari masa kerajaan yang mengabadikan istilah jamu. Beberapa relief di Candi Borobudur, Prambanan, hingga Tegalwangi juga memperlihatkan aktivitas meracik dan meminum jamu.
Prasasti Madhawapura yang jadi peninggalan Kerajaan Majapahit menyebut profesi peracik dan penjual jamu dengan acaraki.
Mengingat bahan baku jamu dari racikan akar, daun, batang, hingga bunga pada tanaman yang diolah menjadi obat-obatan tradisional, tentu saja tiap suku yang mendiami daerah tertentu memiliki warisan pengetahuan ini. Tak terkecuali Suku Kaili yang menghuni Lembah Palu.
Hanya saja kebiasaan menjajakan jamu dengan cara berkeliling sambil digendong lebih populer dilakukan oleh orang-orang Jawa.
Jangan heran jika ada lagi teori lain yang menyebut asal-usul istilah jamu berasal dari gabungan kata “Jawa” dan “Ngramu” (meramu atau mencampurkan). Sederhananya berarti ramuan yang dibuat oleh orang Jawa.
Saat jadi transmigran ke berbagai daerah di Indonesia, kebiasaan atau profesi berjualan jamu masih dipertahankan sebagian dari mereka sehingga penggunaan istilah jamu populer seantero negeri.

Jika sekarang lazimnya penjual jamu dilakukan oleh perempuan, dahulu kala profesi ini juga dilakoni oleh laki-laki.
Zaman lampau budaya meracik dan minum jamu hanya untuk kalangan bangsawan yang menghuni istana kerajaan. Menyadari pentingnya khasiat jamu untuk menjaga kesehatan, lambat laun pihak kerajaan mulai mengenalkan jamu kepada warga secara luas.
Untuk mendorong sistem distribusi jamu kepada masyarakat di luar lingkaran istana, pihak kerajaan biasanya mengutus perempuan dan laki-laki. Sistem pembayaran biasanya dengan barter (jamu ditukar bahan makanan).
Lantaran terasa benar manfaatnya, praktik tersebut lantas menjadi kebiasaan sehingga pengiriman jamu dilakukan secara teratur. Keahlian meracik jamu juga mulai dipelajari oleh masyarakat awam.
Alhasil memicu hadirnya banyak penjual jamu. Mereka berkeliling ke desa-desa. Laki-laki membawa jamu dengan cara memikulnya, sedangkan kaum perempuan menggendong bakul berisi jamu.
Aktivitas menjual jamu kemudian hari lebih sering dilakukan oleh ibu-ibu musabab para suami lebih banyak diperlukan untuk menggarap sawah. Demikianlah kebiasaan tersebut berlangsung hingga sekarang.
Pemerintah Republik Indonesia tahun lalu telah pula mengusulkan budaya sehat minum jamu menjadi warisan dunia tak benda ke UNESCO, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.
Andi Baso Djaya turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
jamu penjual jamu jamu gendong kafe jamu warisan nusantara warisan dunia tak benda UNESCO kearifan lokal obat tradisional herbal