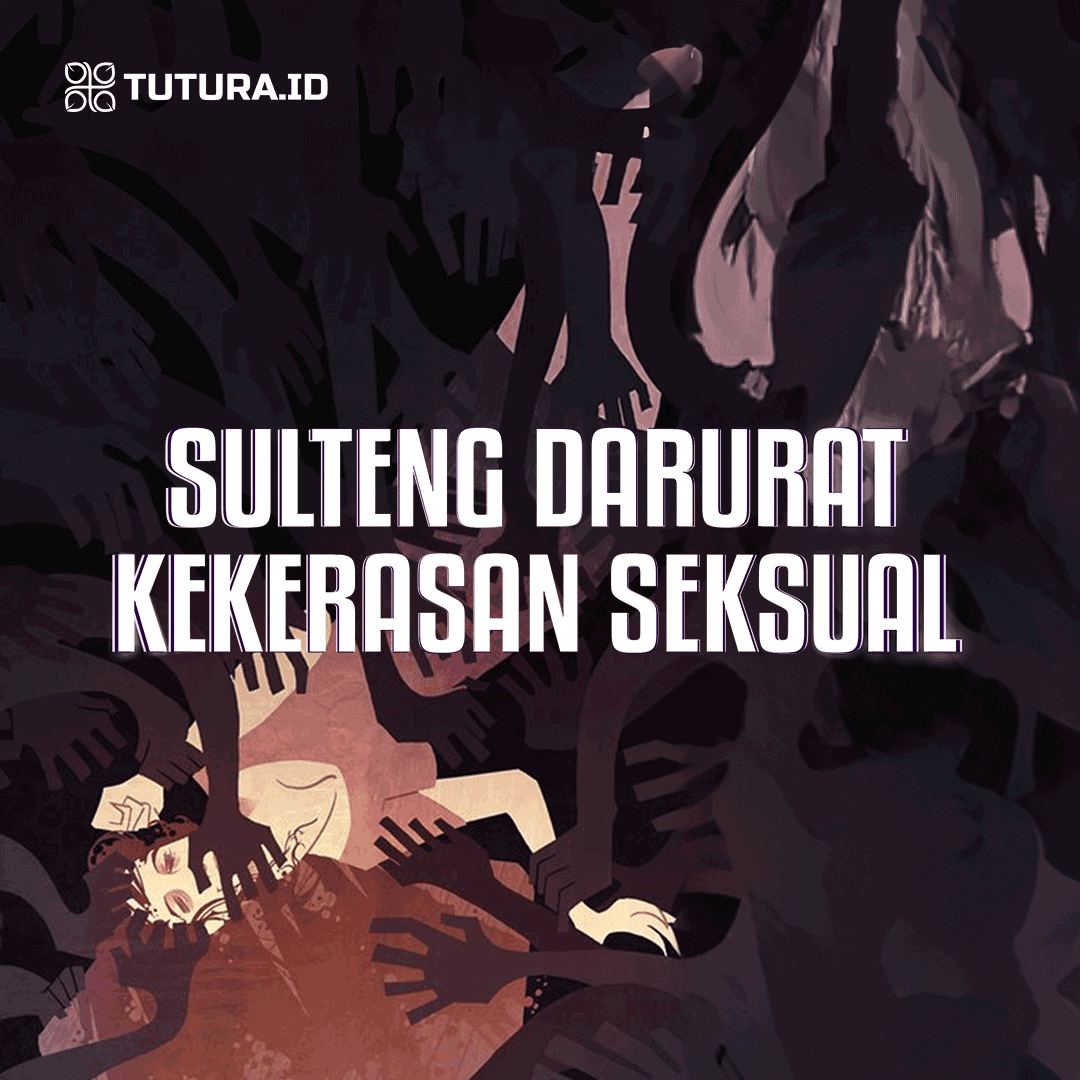Azimut matahari tak lama lagi menyentuh titik sempurna di ufuk barat saat kami tiba di mintakat Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, sekitar sembilan kilometer dari titik nol Kota Palu, Rabu (26/4/2023).
Tujuan kami hendak menemui sekaligus bersilaturahmi di kediaman Tjatjo Tuan Sjaichu Al-Idrus. Sosoknya dikenal luas sebagai pelestari bahasa daerah Kaili, kelompok etnik terbesar yang menghuni Sulawesi Tengah.
Upaya gigihnya itu termaktub dalam berbagai ragam syair dan cerita-cerita pendek. Semuanya ia simpan rapi di rak. Beberapa yang sempat diperlihatkannya kepada kami adalah Soyo Lei, Panembulu, dan Tovau Loba.
Adapun buku yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan adalah Pompatuduki Basa Kaili Rai dan Kamus Bahasa Kaili. “Menurut saya ini perlu sebagai bentuk pelestarian bahasa daerah kita sendiri,” terangnya.
Atjat atau Abah Tjatjo, demikian sapaan akrabnya, hadir menyambut kami mengenakan setelan kopiah putih, baju koko berwarna cokelat, dan sarung bermotif garis-garis. Janggut dan rambut yang menyembul di balik kopiahnya berkilap seputih susu.
Beberapa stoples kue kering tersaji di atas meja. Tak lama berselang tersuguhkan pula teh hangat. “Kalau kalian tidak makan kue dan minum teh ini, saya tidak akan mulai bercerita,” kelakarnya.
Sembari menyesap suguhan teh dan beberapa gigitan kue, takzim kami mendengarkan kisah perjalanan Abah selama puluhan tahun melestarikan dialek Kaili.
Banyak waktu dihabiskannya untuk menulis beragam jenis syair dalam bentuk Bahasa Kaili, Indonesia, bahkan Inggris.
Dalam ilmu dialektologi, dialek secara sederhananya berarti variasi bahasa yang berbeda-beda menurut wilayah atau kelompok orang tertentu.
Lelaki yang lahir di Tanjung Padang, Sirenja, 27 Desember 1949, mulai tertarik menulis dan membaca sejak berumur lima tahun.
“Dulu paman saya bekerja sebagai juru penerangan yang pada waktu itu masih ada Menteri Penerangan. Oleh karena itu, buku-buku tersimpan rapi di lemari,” kenangnya.
Santiniketan karya Rabindranath Tagore, penyair, dramawan, filsuf, dan seniman Bengali peraih nobel di bidang sastra, menjadi buku pertama yang dibacanya.
Menginjak kelas dua sekolah dasar, Atjat telah pula menamatkan novel Merantau Ke Deli dan Di Bawah Lindungan Ka’bah karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah alias Hamka.
Kesukaannya terhadap karya Buya Hamka berlanjut. Atjat lebih memilih tidak makan seharian demi bisa menebus buku Peribadi (terbit pertama kali pada 1950) karya sastrawan, ulama, dan pahlawan nasional asal Minangkabau itu.
“Saya ini berasal dari keluarga guru. Dulu itu ada sekolah guru bantu dan dari situ saya sangat suka membaca dan menulis,” ujarnya.

Ketertarikan berawal dari kecemasan
Setelah menamatkan pendidikan Sastra dan Bahasa Inggris di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Makassar (Sulawesi Selatan), Cabang Palu, medio 1970-an, Atjat bersama sepupunya, Muhammad Nur Lemba dan Najib Habi, mulai tertarik meneliti berbagai dialek dalam Bahasa Kaili.
Pemicu yang melandasinya dari rasa khawatir. Mereka cemas bahwa kelak ragam dialek Kaili akan makin jarang digunakan hingga akhirnya punah tersisa cerita.
Berangkat dari situ mulailah Atjat menyusuri jalan panjang. Ia intens menjumpai sejumlah tetua adat Kaili untuk berdiskusi, bertemu langsung dengan beberapa penutur bahasa Kaili dari kampung ke kampung, dan mulai membahas tentang kesusastraan Kaili.
Berdasarkan hasil perjalanannya tersebut, ia mencatat berbagai dialek Kaili yang tersebar di Sulteng, mulai dari Ledo, Taje, Rai, Da’a, Tara, Unde, Kori, Njedu, Pendau, Doi, Ija, Taa, Ende, Inde, Edo, Ado, Tado, Moma, Ndepuu, Tajio, Sedoa, Tavaelia, Bare’e, dan Tiara. Belum lagi Bahasa Kaili yang memiliki ragam subdialek di bawahnya.
Sementara itu, berdasarkan penghitungan dialektometri bahasa dari Kemdikbud, saat ini Bahasa Kaili hanya menyisakan 10 dialek saja, yaitu Ledo, Taje, Rai, Daa (Da’a), Tara, Unde, Unde Kabonga, Kori, Njedu, dan Pendau
Uniknya semua ragam dialek dalam bahasa Kaili tadi bermakna tidak atau penyangkalan. “Itu menyiratkan kuatnya sifat negasi dalam kehidupan keseharian warga Kaili,” kata Atjat.
Sesal yang dirasakannya sekarang karena beberapa dialek Kaili menuju kepunahan. Kebanyakan anak muda suku Kaili yang ditemuinya langsung juga mengaku tidak bisa berbahasa Kaili. Hanya sekadar tahu artinya. Ada rasa gengsi ketika berkomunikasi menggunakan bahasa daerah.
“Sekitar tahun 80-an waktu saya ke Pewunu, yang menggunakan dialek Ende di sana tinggal satu keluarga terdiri dari empat orang. Saya rasa dialek Ende sudah tidak ada,” lanjutnya lirih.
Kelestarian dialek Taje di Kabupaten Parigi Moutong, Njedu di Kabupaten Donggala, dan Kori di Donggala juga terancam lantaran hanya menyisakan sekitar 20 keluarga yang jadi penutur aktifnya.
Pada 1993, sosok yang masih aktif mengajar di Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Alkhairaat ini pernah mengajak para mahasiswa melakukan penelitian tentang keberadaan Bahasa Kaili.
Kesimpulan penelitian itu tinggal 7,8% saja orang-orang yang bersuku Kaili asli menggunakan dialek Kaili dengan anak-anaknya di dalam rumah. Sementara 46% menggunakan bahasa campuran antara dialek Kaili dan Bahasa Indonesia.
Oleh karena itu, Atjat sangat mengharapkan peran besar pemerintah untuk ikut aktif dalam pelestarian budaya Kaili.
Wujud sederhananya bisa dengan mengadakan berbagai lomba yang menggunakan Bahasa Kaili, semisal baca puisi atau pidato. “Supaya bahasa ini bisa tetap hidup dan tidak menjadi kisah nantinya.”
View this post on Instagram
Tjatjo Tuan Sjaichu Al-Idrus Kaili sastra dialek bahasa budaya Buya Hamka Rabindranath Tagore Palu Donggala Parigi Sulawesi Tengah Kemdikbud