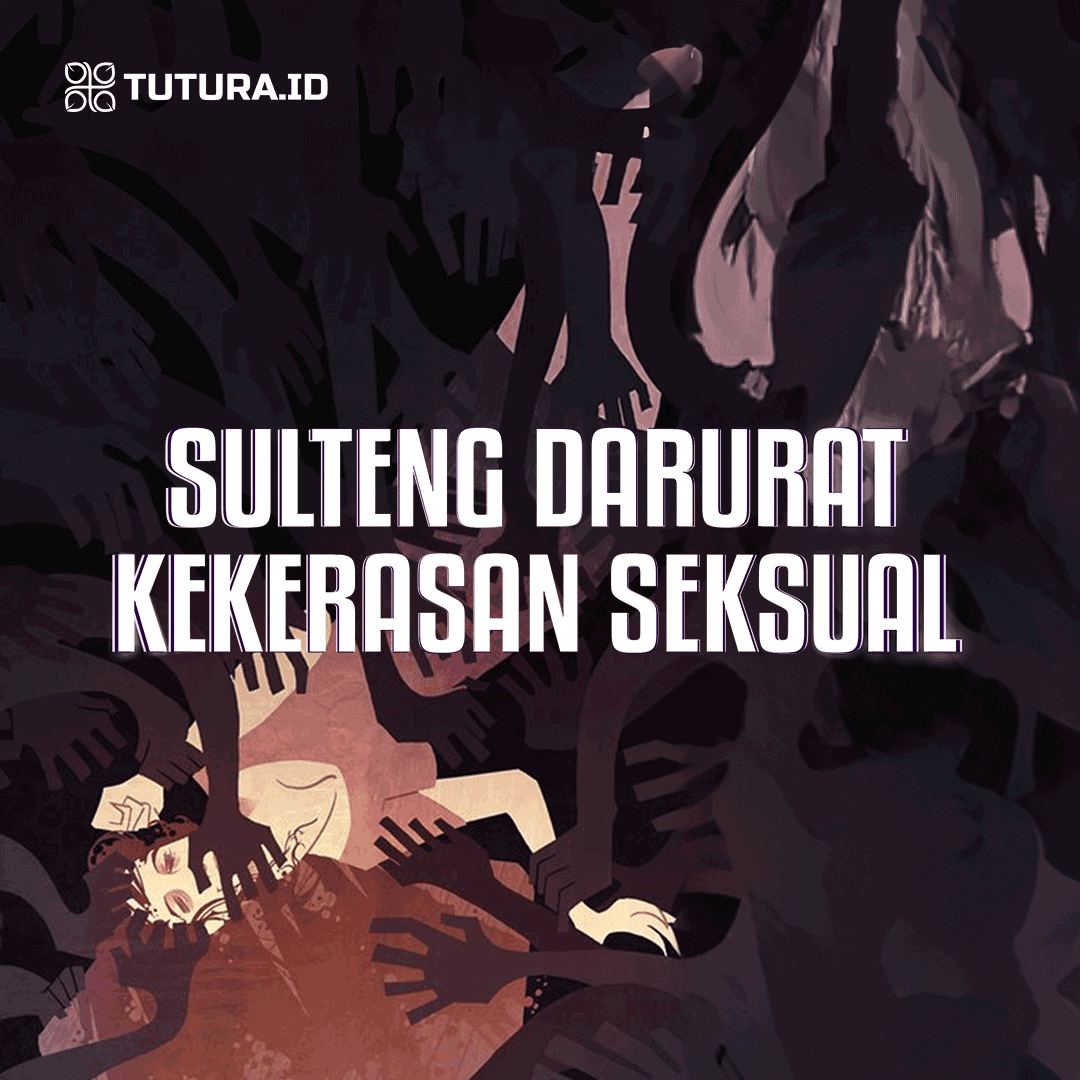Kota Palu berbeda dengan Semarang, Magelang, Jakarta, atau daerah lain yang punya kawasan chinatown alias pecinan yang beraksitektur khas Tionghoa.
Mungkin, lantaran begitu, sebagian warga Palu hanya bisa menerka-nerka permukiman etnik Tionghoa lewat keberadaan ruko milik mereka. Namun bukan berarti Kota Palu tidak memiliki "Kampung Cina."
Pegiat sejarah lokal di Palu, Jefrianto, mengungkapkan bahwa kawasan pecinan di Palu sebagian berada di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat. Sisanya ada di Kelurahan Nunu, dan Bambaru, Kelurahan Baru.
“Pokoknya ada di area Jalan Gadjah Mada, Jembatan I, Jalan Sungai Lariang, sampai Nunu. Di Bambaru juga ada,” kata Jefri, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, Jefri memerinci riwayat warga keturunan Tionghoa di Palu. Berikut lintasan sejarahnya.
***
Keberadaan etnik Tionghoa di Palu sudah ada sejak pertengahan abad 19, atau sekitar 1840-1850. Jalur masuknya lewat Donggala atau Wani.
Sebelum ke Palu, mereka bermukim di daerah-daerah lain, seperti Surabaya, Manado, dan Banjar. Sehingga muncul penyebutan seperti Cina Surabaya, Cina Banjar, Cina Makassar, dan Cina Manado. Atau mungkin yang paling dekat dengan Palu sebutlah Cina Donggala.
Semasa kolonial Belanda masyarakat kerap dikelompokkan berbasis etnik. Masing-masing kelompok punya pemimpin sendiri. Pemerintah Hindia Belanda menyebut para pemimpin ini dengan sebutan kapitan atau kapten.
Sekat semacam itu diniatkan Belanda untuk membatasi pribumi berbaur dengan para perantau.
Namun penduduk Lembah Palu punya karakter terbuka yang mudah menerima para perantau. Itu bikin niat Belanda tak pernah sampai. Nyatanya orang-orang asli Lembah Palu tetap bergaul dengan para pejalan jauh yang berbeda ras, bahasa, hingga warna kulit. Harmonis adanya.
Pemerintah Belanda kemudian membagi Palu menjadi dua kawasan berpatok pada Sungai Palu yang membelah kota.
Sisi barat sungai menjadi Palu Barat, dikenal sebagai distrik perniagaan. Sedangkan Palu Timur menjadi sentra administrasi dan pemerintahan. Tidak seperti masa kini, ketika Palu telah memiliki delapan kelurahan.
Warga etnik Tionghoa ditempatkan di Palu Barat, tepatnya di bilangan Ujuna. Sehingga, pada akhir abad 19, mereka mulai punya ruang untuk berdagang.
Pada dekade pertama abad 20, Palu menjadi kian ramai. Selain Tionghoa, komunitas warga dari Jazirah Arab juga tumbuh pesat. Belum lagi para perantau dari berbagai wilayah di Nusantara, misalnya Bugis, Mandar, Minahasa, Melayu, Minang, dan Banjar.
Kawin mawin antara perantau dengan warga lokal pun terjadi dan berlangsung selama beberapa dasawarsa. Palu tumbuh sebagai rumah bersama dengan keragaman suku .
Seperti topografinya yang serupa kuali lantaran dikelilingi pegunungan, Palu jadi salah satu melting pot (kuali peleburan) di Pulau Sulawesi. Tempat meleburnya macam-macam kebudayaan. Masyarakat yang semula cenderung homogen menjadi heterogen; lantas melebur (lagi) jadi satu.

Etnik Tionghoa terkenal dengan semangat kerja dan keuletannya. Aktivitas utama mereka ialah berdagang. Seperti banyak daerah di Indonesia, satu jejak perdagangan yang paling terlihat dari warga Tionghoa di Palu adalah warung kopi.
Kopi susu yang sekarang kita nikmati di warkop rasa-rasanya boleh disebut sebagai jejak kuliner terbaik yang disumbangkan oleh etnik Tionghoa untuk Palu.
Selain berdagang, mereka juga punya andil di lini pendidikan. Jejaknya terukir lewat keberadaan sekolah Chung Hwa Xue Xiao. Secara harafiah “chung hwa” berarti “keturunan Tionghoa” dan “xue xiao” bermakna "sekolah."
Kontrolir Palu, J.A. Vortsman dalam sebuah laporannya (1935) menulis ada tiga jenis sekolah di Palu, yakni: Sekolah Partikelir Belanda (Part. Holland Inlandsche School), Sekolah Tionghoa, dan Sekolah Agama Islam. Chung Hwa Xue Xiao disebut sebagai Sekolah Tionghoa dalam laporan itu.
Bangunan sekolah ini terletak di Jalan Gadjah Mada, Lorong Bakti. Pada medio 1970-an, bangunan yang kini telah jadi rumah pribadi itu pernah menjadi kampus cabang untuk IKIP Makassar--sekarang Universitas Tadulako.
***
Tahun terus berlanjut. Berganti jadi pancawarsa, windu, lalu dasawarsa. Palu semakin ramai lagi sibuk. Ekonomi terus tumbuh. Pelaku ekonomi datang dari berbagai penjuru.
Kota Palu memang cukup strategis menampung hasil bumi. Tercatat, sejak 1920, Palu jadi salah satu pusat utama penampungan kopra.
Di masa lalu, istilah "tauke" sering dipakai guna menyebut para bos kopra atau kelapa beretnik Tionghoa. Kecakapan warga Tionghoa dalam perdagangan memang memainkan peran penting bagi industri kopra yang jadi andalan Palu.
Kian hari makin banyak warga Tionghoa yang tinggal dan menetap di Palu. Sehingga, berdasarkan catatan Departement van Economische Zaken pada 1930, jumlah Etnik Tionghoa di Palu mencapai 433 jiwa. Komposisinya terdiri dari 261 laki-laki dan 172 perempuan.
Jumlah ini hanya mencapai 0,62 persen dari total penduduk Palu saat itu, yang mencapai 69.610 jiwa.
Namun, warga Tionghoa mendominasi di antara orang-orang keturunan negeri nan jauh. Total warga keturunan saat itu mencapai 713 jiwa. Alhasil persentase warga Tionghoa di antara orang-orang keturunan mencapai 60,7 persen.
Adapun jumlah warga Tionghoa dibandingkan dengan wilayah lainnya di Sulteng ialah: 698 jiwa di Donggala, 612 jiwa di Toli-toli, dan 429 jiwa di Buol. Dalam lingkup nasional, pada 1930, etnik Tionghoa telah mencapai 2,3 persen di Indonesia.
Tionghoa Imlek sejarah tionghoa di palu palu etnik budaya sejarah jerfrianto komunitas historia