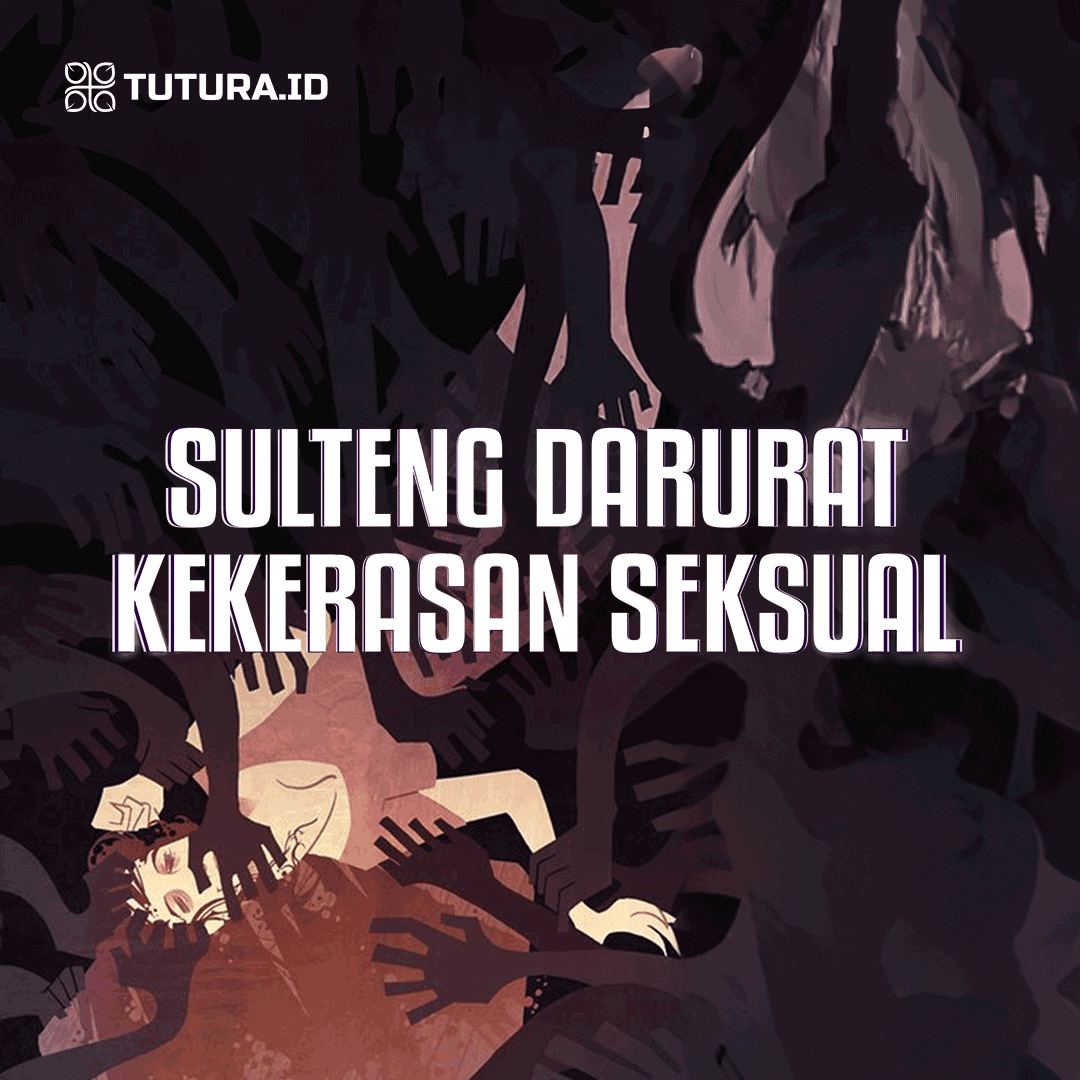Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengakui adanya 12 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di Indonesia. Presiden juga memerinci 12 kasus tersebut dalam pengumumannya di Istana Negara, Rabu (11/1/2023).
Beberapa di antaranya merupakan kasus di bawah era 2000-an, yakni: Peristiwa 1965-1966; Penembakan Misterius 1982-1985; Talangsari, Lampung 1989; Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989; Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998; Kerusuhan Mei 1998; Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999; Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999; dan Simpang KKA, Aceh 1999.
Ada pula tiga kasus yang terjadi di atas 2000-an: Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002; Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.
Presiden Jokowi pun menyampaikan rasa simpati dan empati mendalam kepada para korban beserta keluarga. “Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial,” kata Jokowi.
Ia juga meminta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md untuk memastikan agar pelanggaran HAM berat tak terulang lagi di masa mendatang.
Menko Mahfud, dalam interviu bersama Kompas TV (15/1/2023), menyebut bahwa fokus pemerintah ialah merehabilitasi hak korban beserta keluarganya. Konon, Jokowi bakal bikin rapat khusus bersama sejumlah kementerian dan lembaga guna memastikan rehabilitasi ini.
“Ini korban yang jadi fokus kita, bukan pelaku,” ujar Mahfud. “Karena kalau bicara soal pelaku, amat sangat sulit, dan itu hanya bisa pengadilan yang memutuskan.”
Adapun pengakuan pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari laporan Tim Non-Yudisial Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) yang telah diserahkan ke Menko Mahfud pada akhir Desember 2022. Tim PPHAM dibentuk Presiden Jokowi lewat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.

Tak cukup sekadar pemulihan hak korban
Pengakuan dan pernyataan Presiden Jokowi menuai respons negatif dari kalangan pegiat HAM. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pengakuan tersebut, “Tidak ada artinya tanpa pertanggungjawaban hukum dan keadilan bagi korban.”
Usman bilang pengakuan tanpa upaya mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab pada masalah pelanggaran HAM hanya menambah garam pada luka para korban. “Sederhananya, pernyataan Presiden tersebut tidak besar artinya tanpa adanya akuntabilitas,” kata Usman.
Amnesty International Indonesia juga menyayangkan sikap pemerintah yang membatasi pengakuan hanya pada 12 kasus pelanggaran HAM berat. Padahal, ada sejumlah kasus lain yang punya derajat tak kalah penting.
Beberapa kasus yang terabaikan dalam pernyataan Jokowi itu, antara lain pelanggaran yang terjadi selama operasi militer di Timor Timur, peristiwa Tanjung Priok 1983, kasus 27 Juli 1996, hingga perkara pembunuhan Munir Said Thalib.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga punya catatan senada. KontraS bahkan bilang bahwa pengakuan ihwal adanya kejahatan kemanusiaan bukanlah hal baru. Sejak 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi semacam ini.
“Pengakuan dan permintaan maaf harus ditindaklanjuti dengan rangkaian tindakan untuk memberikan hak-hak korban secara keseluruhan berupa pengungkapan kebenaran dan upaya pemulihan sesuai dengan hukum, tidak sekedar jaminan sosial,” demikian pernyataan KontraS.
Sebagai catatan, bila pemulihan hak korban sekadar dimaknai sekadar jaminan sosial, bahkan Kota Palu pun sudah melakukannya.
Semasa Rusdy Mastura menjabat wali kota Palu telah terjadi pengakuan atas pelanggaran HAM pada peristiwa 1965-1966. Pemerintah Kota Palu mengakui dan merehabilitasi hak korban lewat skema jaminan sosial, rehabilitasi fisik, psikis, hingga pemberian beasiswa.
KontraS juga menyatakan ada beberapa tim yang pernah dibentuk oleh Presiden Jokowi soal pelanggaran HAM berat. Mulai dari Komite Rekonsiliasi dan Komite Pengungkapan Kebenaran pada 2015; hingga Tim Gabungan Terpadu Tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu pada 2018.
Semuanya, dalam pandangan KontraS, “Terbukti gagal untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat secara akuntabel dan justru hanya memperalat korban untuk melegitimasi formalitas “penyelesaian” di permukaan saja.”
Ada pula kekhawatiran bila pengakuan ini tidak diikuti dengan insiatif mereformasi TNI dan Polri secara struktural maupun kultural. Kedua lembaga tersebut memang rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM berat.
KontraS juga menyoroti perkataan pemerintah ihwal empat pengadilan HAM yang disebut kurang bukti dan mengakibatkan terdakwa bebas. Dalam perspektif KontraS, negara harus menjamin pertanggungjawaban hukum dan memastikan aparat penegak hukum kompeten.
“Pernyataan Presiden Joko Widodo yang berangkat dari rekomendasi Tim PPHAM kami khawatirkan sebagai gula-gula yang menempatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat hanya mendorong pada mekanisme non-yudisial sekaligus mewajarkan praktik pengabaian terhadap pengadilan HAM yang buruk,” begitu kesimpulan KontraS
Para korban kasus pelanggaran HAM berat juga menyatakan harapan senada, yang lebih dari sekadar pengakuan.
Maria Catarina Sumarsih, ibu dari korban peristiwa Semanggi, juga menyatakan hal senada dalam wawancara yang dilansir dari Kompas.com. “Pelanggaran HAM berat masa lalu tidak perlu disesali, tetapi harus dipertanggungjawabkan di Pengadilan HAM ad-hoc," kata Sumarsih.
BBC Indonesia mengutip pernyataan Frans Saba yang merupakan korban peristiwa Wasior di Papua pada 2001-2002. Ia juga berharap agar kasus ini diproses secara hukum, tidak semata-mata jalur non-yudisial.
"Jadi bagi kami penyelesaian hari ini tidak cukup. Kalau tidak ada proses hukum justru pemerintah membangun masalah baru. Mereka yang meninggal itu bukan binatang, tapi manusia," ujar Frans Saba.
Jokowi presiden jokowi ham hak asasi manusia mahfud md kontras amnesty international pelanggaran ham tni polri