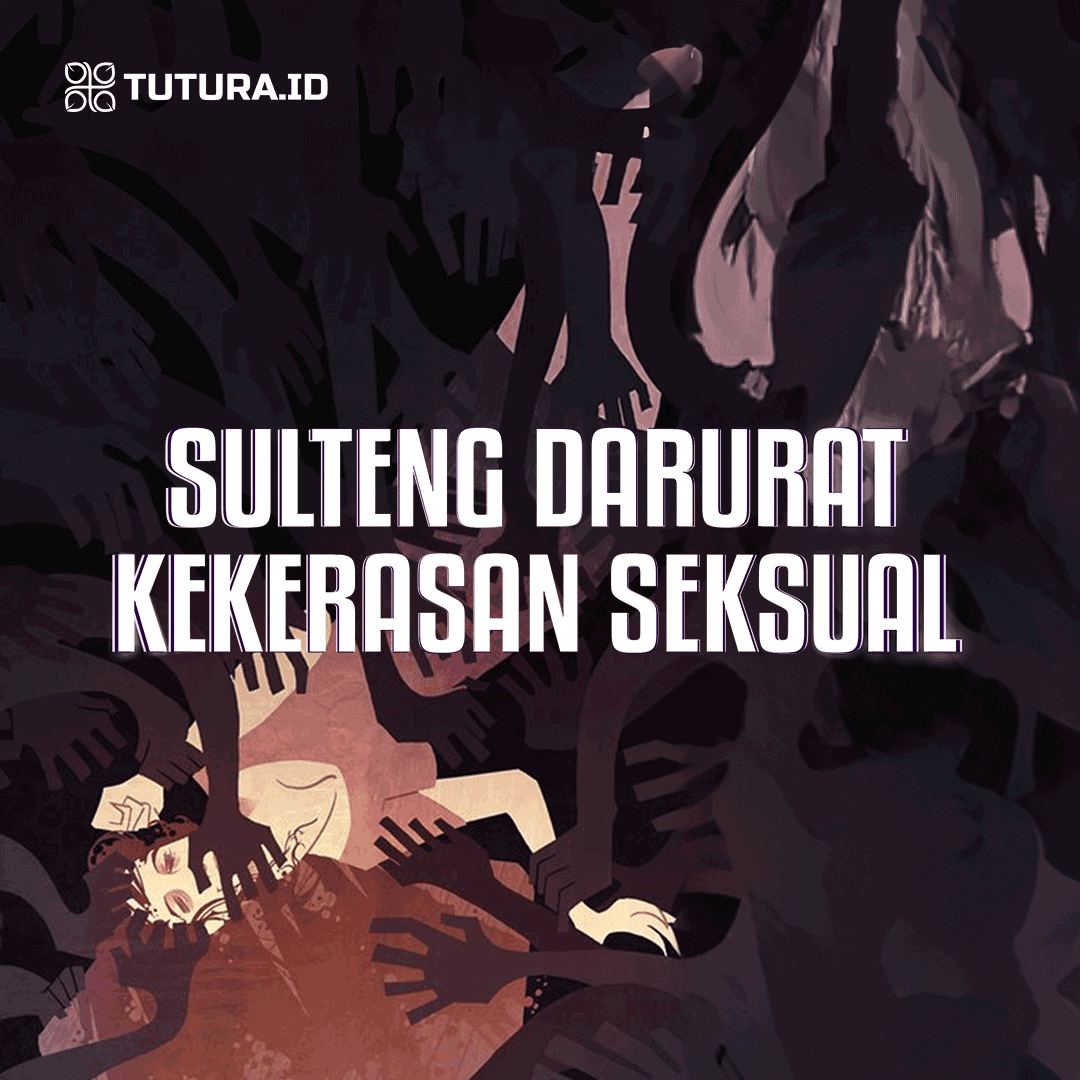Polemik antara musisi dengan event organizer (EO) alias penyelenggara acara seperti lagu lama yang tak henti terputar ulang. Perdebatan tentangnya selalu hadir mewarnai tumbuh kembang industri musik di Kota Palu. Pun wilayah-wilayah lain di negeri ini yang senasib.
Bukan sekadar topik perbincangan yang beredar di kalangan internal atau percakapan di warung kopi semata, tapi juga memancing perdebatan di lingkup lebih luas dan tak terkendali; media sosial. Niatnya mulai dari semata curhat hingga saling tuding.
Pihak sini menyindir sana lantaran kerap berlaku tidak adil terhadap talenta-talenta lokal. Diskriminatif. Banyak contoh dimunculkan sebagai penguat argumen, mulai dari soal rendahnya daya tawar perkara honorarium manggung, pelayanan berbeda di belakang panggung, hingga merembet ke persoalan teknis soal jatah penggunaan volume maksimal tata suara.
Kecuali faktor pertama yang sifatnya urusan dapur masing-masing, dua unsur lain di atas nyata belaka. Penonton bisa dengan jelas membedakan ukuran tenda untuk talenta pendukung dengan artis utama berikut isi di dalamnya.
Urusan peruntukan tata suara juga bisa terukur mudah di kuping. Band pembuka, dalam konteks ini menjadi jatah musisi lokal, kerap kalah gahar semburan sound system-nya kala beraksi di atas panggung. Beda jauh saat penampil utama dari ibu kota giliran beraksi. Lebih menggelegar.
“Menurutku yang ada hanya EO dagang. Pertimbangan mereka murni cari untung, tidak mau rugi. Musisi jadinya diperlakukan seperti barang. Harga masuk lanjut. Tidak masuk, ya, lepas,” ujar Umariyadi Tangkilisan, gitaris band Culture Project sekaligus Ketua DPD PAPPRI Sulteng kepada Tutura.Id melalui pesan singkat (8/10/2022).
Apa yang dikemukakan Adi, sapaan akrab Umariyadi, meski bersifat personal seolah mewakili suara musisi lain. Dalam beberapa pertemuan yang diselenggarakan PAPPRI Sulteng bersama para seniman lain, praktik kerja sama ala toko kelontong ini kerap mengemuka jadi topik diskusi.
Ikhtiar untuk coba mengubah pola kerja yang membuat daya tawar anak band rendah tadi bukannya tidak pernah dilakukan. “Jauh sebelum PAPPRI Sulteng terbentuk sudah ada usaha dari beberapa teman musisi untuk kompak. Pokoknya mereka sepakat menolak kalau diajak main dengan bayaran kecil. Cuma kembali lagi, kebutuhan band dengan masing-masing personelnya itu beda-beda,” terang Adi.
Ada musisi atau band yang tetap bersedia tampil meskipun tawaran honor yang mampir di bawah patokan mereka selama ini. Pertimbangannya banyak. Demi menjaga dapur tetap menyala salah satu faktor. Alasan lain tidak melulu soal angka. Untuk menjaga eksistensi, misalnya. Maka jadi penting untuk kerap hadir dalam berbagai panggung. Menambah jam terbang dan pengalaman.
Pendorong lain karena ingin memanfaatkan berjubelnya massa penonton yang datang lantaran ingin menyaksikan penampilan artis idola dari ibu kota. Kondisi demikian, bagi musisi atau band yang baru saja merilis album atau karya, bisa dimanfaatkan sekaligus sarana promosi.
Hal lain yang sifatnya selintas terdengar “remeh-temeh” juga ada. “Bagi kami, band anu adalah idola. Jadi waktu ditawarkan sebagai band pembuka mereka, kitorang langsung setuju. Kendati tidak dibayar tidak apa-apa,” demikian kurang lebih ilustrasinya.
Tentu saja tidak ada yang salah dengan segala keputusan tersebut. Hanya yang patut dipertanyakan—atau disesalkan—jika misalnya penyelenggara acara keenakan memanfaatkan posisi tawar tersebut sehingga abai berlaku secara profesional.
Kurangnya profesionalisme segelintir EO di kota ini turut pula mewarnai perjalanan karier Hilwa Humayrah, manajer Culture Project dan The Mangge.
Rupa-rupa pengalaman didapatkannya, mulai dari etika tidak santun dari penyelenggara acara saat melakukan komunikasi, hingga menganggap Culture Project “kemahalan”.
“Untuk menjawabnya saya selalu bilang bahwa saya tidak memahalkan, tapi mencoba untuk merasionalkan harga karena Culture Project itu bukan cuma para personel. Ada tim manajemen yang isinya terdiri dari beberapa orang tenaga profesional di bidangnya masing-masing. Timnya Culture Project sekarang itu total 11 orang. Dan karya yang dibawakan Culture Project itu bukan sekadar lagu yang dibawakan secara musikal, tapi dari melalui hasil riset,” jelas Hilwa kepada Tutura.Id yang menemuinya di Sub Plaza, Jl. Dr Jl. Sam Ratulangi, Palu Timur (1/10).
Kali lain, terkadang mampir pula pernyataan pedas berbunyi; “Kamorang minta harga segitu, memangnya bisa datangkan berapa banyak penonton?”
“Nah, ini jadi semacam motivasi dan pekerjaan rumah bagi Culture Project. Supaya kami tidak hanya dibawa, tapi juga harus bisa membawa massa untuk datang ke sebuah acara yang sudah mengundang kami. Bagaimanapun kami ini ada di industri. Hitungannya bisnis. Jadi suka atau tidak suka kami juga harus memikirkan itu,” tutup Hilwa.
Para penyelenggara acara yang murni berjalan dengan berbagai parameter bisnis menurut hemat Adi tetap harus dihargai. Yang harus disediakan adalah opsi. Oleh karena itu, ia mengharapkan juga kemunculan EO yang bergerak tidak semata untuk mencari keuntungan.
“EO yang menjadikan musisi sebagai partner kerja, yang dalam prosesnya mengikutkan musisi dalam strategi promosi dan penyajian, baik menargetkan segmen penonton dan jejaring kerja yang berkelanjutan bagi karier musisi potensial,” harapnya.
.jpg)
Budi Hi. Lolo, salah satu pendiri LebahMadu Organizer sejak akhir 2014, coba membagikan perspektifnya terkait polemik dua kutub yang sejatinya bertautan dalam ekosistem musik ini. Tutura.Id menemui Budi di kantornya yang terletak di Jalan Setiabudi No. 109, Palu Timur (4/10).
Hal pertama yang coba ia klarifikasi terkait perbedaan antara musisi lokal dengan artis utama, katakanlah yang datangnya dari Jakarta. Baginya artis lokal dengan ibu kota punya posisi berbeda.
“Mereka itu, bahasa pasarnya, sudah terkenal. Karena itu, kehadirannya kita butuhkan untuk menarik massa datang ke acara. Ini ada sebuah acara dengan panggung yang disaksikan banyak orang, silakan teman-teman perkenalkan dan narasikan karyanya teman-teman. Perspektif ini yang saya minta tolong untuk dipahami bersama. Jangan di balik bahwa kami mendiskriminasi musisi lokal. Bukan itu maksudnya. Walaupun wajar saja menurutku kalau ada beda persepsi karena mungkin teman-teman di luar sana juga tidak tahu kendala apa saja yang kami hadapi,” jelasnya.
Ditambahkannya bahwa semisal semua keputusan ditentukan olehnya, maka apresiasi yang tinggi pasti diberikannya kepada musisi lokal. “Saya rasa bukan cuma saya, semua juga mau. Cuma mungkin belum sekarang. Band-band besar dari ibu kota yang sekarang jadi artis utama juga awalnya melewati apa yang kita hadapi sekarang. Semua pasti ada waktunya.”
Perkara gosip penawaran honor manggung kepada musisi lokal yang masuk kategori “ukur tobat” rendahnya, Budi menjelaskan sekilas alur kerja yang kerap dilakoninya. Sebagai bisnis yang berjalan dengan model Business to Business, artinya penjualan produk atau penawaran jasa yang diberikan oleh satu unit bisnis kepada pelaku unit bisnis lainnya, maka ada tiga pihak yang terlibat dalam proses negosiasi, yaitu klien sebagai sang empunya hajatan sekaligus pendana, EO yang dipercaya mengelola acara tersebut agar sukses, dan para talenta pengisi acara.
Musisi sebagai talent mematok harga sekian kepada EO. Lalu pihak EO menyodorkan harga tersebut kepada klien. Tentu dengan jumlah yang sudah tidak sama lagi. Hal lumrah dalam dunia pertunjukan. “Itu sah. Semua EO saya rasa juga melakukan hal serupa,” ungkap Budi.
Ihwal mengapa jumlah angka tersebut berubah dikarenakan semua hal terkait talent menjadi tanggung jawab EO di hadapan klien. Segala keluhan atau protes klien terhadap para penampil pasti ditumpahkan kepada mereka selaku penyelenggara acara, bukan kepada para talent. Pun demikian, sebelum menemukan titik kesepakatan, tiga mata rantai yang saling terlibat ini melakukan apa yang namanya negosiasi.
Masing-masing pihak punya kuasa untuk menolak atau mengatakan tidak jika sepanjang proses negosiasi gagal menemui kesepakatan. Tidak ada pemaksaan. “Berarti memang belum berjodoh. Ibarat akad. Kalau cocok kita jalan, kalau sebaliknya, ya, berarti tidak jadi. Biasa terjadi,” sambungnya.
Hanya saja secara etika bisnis, lanjut Budi, pihaknya tidak mungkin menyodorkan angka terlalu rendah kepada talent hasil kesepakatan dengan klien. Juga sebaliknya, tidak mengatrol terlalu tinggi fee yang semula diminta talent kepada klien.
“Band atau musisi profesional papan atas pasti pernah juga tidak mencapai kesepakatan bermain dalam sebuah acara, tapi mereka tidak ribut-ribut. Karena persoalan deal atau no deal merupakan hal biasa dalam industri ini. Jadi saya melihatnya ini persoalan komunikasi saja,” kata Budi.

Perihal komunikasi yang menimbulkan polemik berulang ini juga yang menjadi sorotan utama PAPPRI Sulteng dalam rangkaian kegiatan Ecosystem Music Fair 2022. Oleh karena itu, berbagai ajang diskusi dengan tema seputar ekosistem musik turut diselenggarakan.
Usai “Ngobrol Audio” dan “Sosialisasi Hak Cipta”, rangkaian EMF akan berlanjut dengan mengadakan diskusi tentang “Jurnalisme Musik” di Renjana Café (5/11), “Ngobrol Industri Musik” di Sub Plaza (5/11), dan “Manajemen Artis” di Bandsaw Fishing and Resto (6/11). Wendi Putranto (mantan jurnalis musik dan manajer Seringai), David Karto (pendiri Demajors), dan Ardy Chambers (promotor musik) dijadwalkan hadir sebagai narasumber dalam forum diskusi tersebut.
Diadakannya berbagai sesi diskusi tersebut selain bertujuan menambah literasi terkait industri musik, juga diharapkan menjadi episentrum yang mempertemukan semua pelaku industri musik di Sulteng, khususnya di Palu, untuk saling menyambung komunikasi, sinkronisasi, bahkan momen awal menjalin kolaborasi. Harapannya kelak ekosistem musik di kota ini bukan hanya bertambah secara kuantitas, tapi juga makin berkualitas. Ujung-ujungnya nanti bisa ikut menggerakkan subsektor kreatif lain.
Adi Tangkilisan mengakui ekosistem industri musik di Palu—bahkan Sulteng—masih tercerai berai. Belum terbentuk sempurna. Menjadi fokus PAPPRI Sulteng untuk coba merapikan itu semua. Kelak saat ekosistem industrinya sudah terbentuk dan berjalan lancar, pasar akan tercipta dengan sendirinya. Ada yang memang tujuannya jualan laiknya toko kelontong, tapi ada juga yang sifatnya warung-warung apresiasi.
“Saya sebagai EO sangat menyambut baik adanya EMF 2022. Saya akan tetap datang meski, misalnya, tidak diundang karena penyelengaranya teman-teman asosiasi. Alasan saya ngotot mau datang karena pasti akan ada standar bagus yang keluar dari hasil diskusinya. Misalnya PAPPRI Sulteng mengeluarkan daftar band atau musisi yang telah melalui hasil kurasi berdasarkan standar-standar yang sudah mereka tentukan. Kami sebagai EO jelas sangat terbantu. Hasil kurasi tersebut bisa langsung kami gunakan sebagai rekomendasi kepada klien jika nanti mendapat kepercayaan mengelola sebuah acara yang membutuhkan suguhan musik,” pungkas Budi.