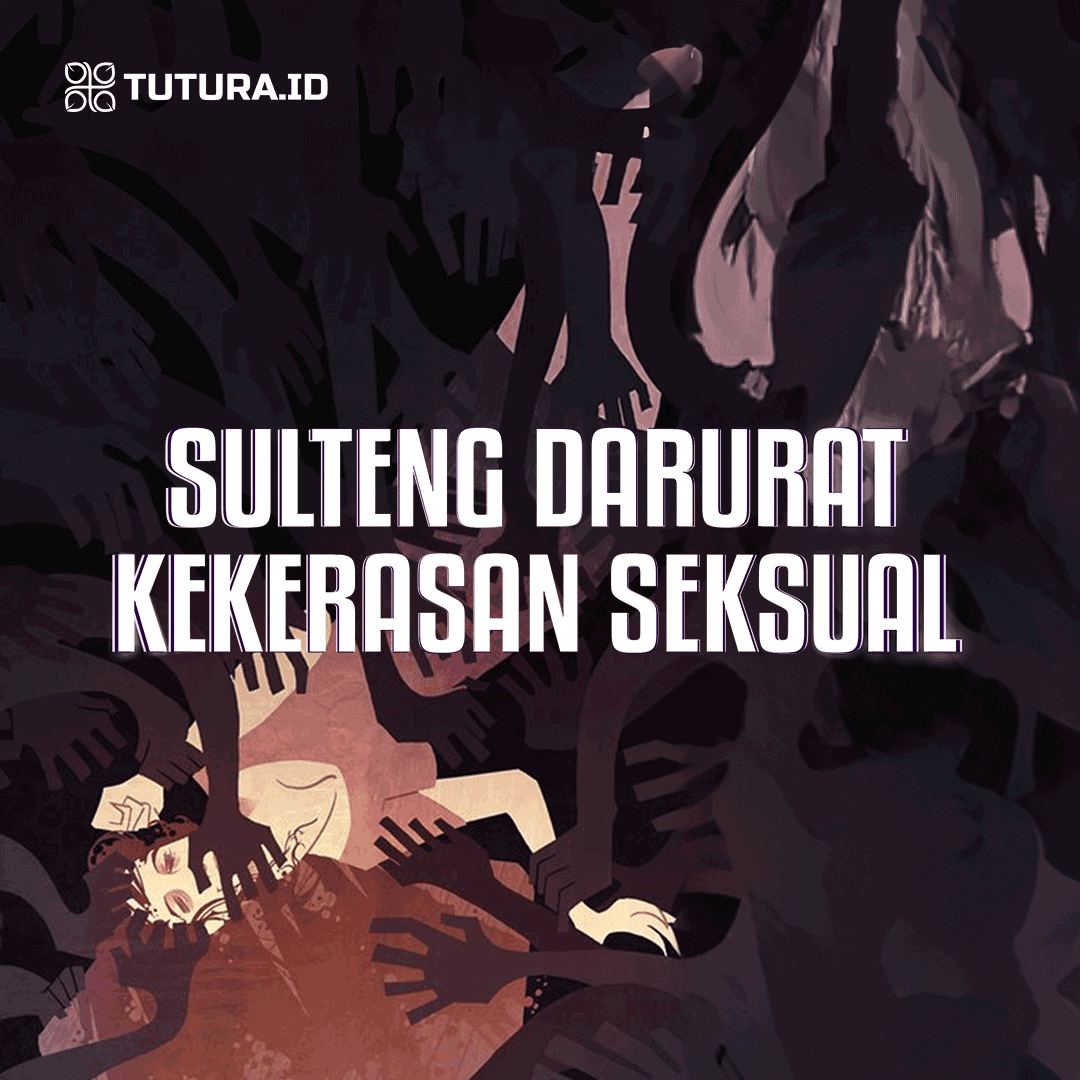Peran etnis Tionghoa yang telah berabad-abad bermukim di Nusantara tidak hanya tersua dalam bidang ekonomi melalui perdagangan. Kelompok masyarakat ini—totok maupun peranakan—telah hadir memberikan sumbangsihnya melalui berbagai bidang, mulai dari politik, militer, seni budaya, kuliner, bahasa, gaya pakaian, hingga arsitektur bangunan.
Bertalian dunia pendidikan, khususnya di Lembah Palu, darma mereka bisa kita telusuri melalui sebuah bangunan yang berlokasi di Lorong Bhakti, tepat berhadapan dengan gang Kelenteng Kwan Im Miau di poros Jalan Gajah Mada, Kelurahan Ujuna, Palu Barat. Sebuah kawasan yang bahkan hingga sekarang ibarat kawasan pecinan di kota ini.
Para warga sekitar menyebutnya Sekolah Cina. Sebutan yang sebenarnya tidak meleset karena ketika awal berdiri sekolah itu resminya bernama Chung Hwa Xue Xiao. “Chung Hua” adalah sebutan untuk warga etnis Tionghoa, sedangkan “Xue Xiao” berarti sekolah.
Saat kaki melangkah makin dekat, tampak sorak keriangan bocah-bocah yang sibuk bermain sambil berkejaran di sekitar bekas kompleks sekolah tersebut. Saya membayangkan berdekade lampau keriuhan yang sama juga hadir dari aktivitas para murid dan guru.

Kompleks ini aslinya terdiri dari tiga bangunan utama. Hanya tersisa dua saja yang masih bisa kita jumpai sekarang. Sementara graha satunya lagi, yang menjadi pusat proses belajar mengajar kala itu, sudah tak berwujud. Berganti jadi semacam taman mini yang terawat bersih. Asri.
Sekeliling kompleks kini telah padat oleh rumah-rumah warga. Ada juga yang modelnya indekos terdiri dari enam petak. Pun dengan dua bekas bangunan di sekolah ini. Dijadikan tempat tinggal, sekalipun secara kasat mata tampak sudah kusam dan ringkih termakan usia.
Keberadaan Chung Hwa Xue Xiao di Kota Palu, juga di daerah-daerah lain, merupakan bentuk keinsafan komunitas warga Tionghoa tentang pentingnya arti pendidikan bagi generasi penerus.
Jika kita menerka lembar perjalanan sejarah, lahirnya sekolah-sekolah tadi sekaligus respons masyarakat Tionghoa terhadap segregasi yang dilakukan pemerintah kolonial dalam bidang pendidikan.

Mereka yang boleh mengenyam dunia pendidikan formal hanya anak-anak berkebangsaan Belanda, Eropa, atau warga lokal dari kalangan ningrat. Kondisi tersebut membuat komunitas, kelompok masyarakat, organisasi sosial, atau tokoh keagamaan dan politik yang selama ini dikucilkan ramai-ramai mendirikan sekolah untuk kalangannya sendiri.
Sebut misal etnis Arab yang mendirikan Jamiat al-Khair sebagai salah satu institusi belajar mengajar untuk kelompoknya. Dalam konteks lokal Palu, Sayyid Idrus bin Salim Aljufri atau Guru Tua yang notabene berasal dari Hadramaut, Yaman, berjasa melahirkan Lembaga Pendidikan Islam Alkhairaat pada 1930.
Merujuk artikel "Chung Hwa Xue Xiao: Identitas Baru Eksistensi Masyarakat Tionghoa di Palu" dalam laman journastoria.com yang ditulis oleh Jefrianto, hampir pada periode bersamaan Liem Pok Tjin, seorang perantau asal Pulau Pingtan di Provinsi Fujian, Tiongkok, juga menggagas berdirinya sekolah Chung Hwa Xue Xiao di atas lahan seluas 4000 meter persegi yang tadi sudah saya kunjungi.

Menghapus prasangka negatif
Kontrolir Palu J.A. Vorstman pada 1935 menulis dalam laporannya bahwa di Kota Palu kala itu hanya ada tiga jenis sekolah yang tidak mendapat subsidi Pemerintah Hindia Belanda, yaitu sekolah partikelir Belanda (Part. Holland Inlandsche School), sekolah Tionghoa (Chinese School), dan sekolah agama Islam yang besar kemungkinan merujuk Alkhairaat.
Chung Hwa Xue Xiao sesuai gagasan awal pendiriannya hanya mengkhususkan diri menerima murid-murid dari kalangan etnis Tionghoa. Pengantarnya pun lebih banyak menggunakan Bahasa Mandarin. Jumlah kelas masih sangat terbatas.
Kondisi tadi berubah setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadi pembaruan berupa penggunaan Bahasa Indonesia sebagai pengantar utama dalam proses belajar mengajar.
Jumlah kelas Chung Hwa Xue Xiao juga terus berkembang. Semula terdiri hanya beberapa ruangan, lalu meningkat jadi 12 ruangan untuk kelas satu hingga enam. Setiap kelas terdiri dari dua ruangan yang masing-masing diisi sekitar 40 siswa.

Perkembangan itu membuat pengelola Chung Hwa Xue Xiao mengeluarkan kebijakan menerima siswa di luar masyarakat Tionghoa. Alhasil murid-murid yang menimba ilmu di sana berasal dari beragam latar suku, ras, dan agama. Multikultural. Para siswa, tenaga pengajar, dan orang tua murid akhirnya guyub dalam perbedaan. Saling menghargai satu sama lain.
Selain jadi bukti betapa etnis Tionghoa cakap dalam membaur dengan warga sekitar, ini sekaligus menepis anggapan bahwa mereka lekat dengan yang namanya eksklusivitas. Prasangka bahwa mereka emoh bergaul dan menutup diri terhadap orang-orang di luar golongan atau kelompoknya terbantahkan.
“Sekolah itu bukan hanya untuk mereka. Warga lokal juga diperbolehkan sekolah di situ. Jadi masyarakat ingat (kebaikan) itu,” ujar Jefrianto selaku pegiat sejarah Kota Palu.
Kebajikan tersebut yang membuat anak-anak etnis Tionghoa tetap mendapat tempat saat Chung Hwa Xue Xiao terpaksa tutup lantaran imbas gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) pada 1957. Gedung sekolah dijadikan asrama tentara Bataliyon 758 pimpinan Frans Karangan.

Demi bisa terus melanjutkan pendidikan dan tidak putus sekolah, murid-murid di sana pindah ke Sekolah Muhammadiyah. “Coba kita pikir, kalau tidak diterima bagus sama masyarakat lokal sini, tidak mungkin dorang mau diterima sekolah di situ,” tambah Jefri.
Ketika keadaan kota sudah kondusif, sekolah kemudian dibuka kembali. Hanya saja bayang-bayang penutupan kembali hadir. Kali ini seturut wacana penghapusan sekolah partikelir asing.
Melalui Peperpu/012/1958, Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat menintervensi kewenangan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PPK) dan Kementerian Agraria untuk mengurangi kuantitas sekolah-sekolah asing yang beroperasi di Indonesia.
Pengurangan atau penutupan dilakukan secara bertahap selama kurun 1958-1959. Chung Hwa Xue Xiao lolos dari kebijakan tersebut lantaran warga menganggapnya bukanlah sekolah asing, melainkan bagian dari mereka.

Berselang sekian tahun kemudian, imbas peristiwa Gerakan 30 September 1965, sekolah ini akhirnya tutup untuk selamanya. Banyak orang yang beretnis Tionghoa jadi korban asal tangkap karena stigma komunis yang dilekatkan kepada mereka. Kejadian tersebut meruncing hingga di kalangan akar rumput.
Setelah ditutup, kompleks Chung Hwa Xue Xiao dijadikan tempat penahanan orang-orang yang tertuduh sebagai anggota atau terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia.
Akhirnya pada 1974, Chung Hwa Xue Xiao direlokasi ke Jalan Danau Poso yang kita kenal sekarang menjadi Sekolah Katolik (RK).
Gedung-gedung sekolah yang ditinggalkan itu kemudian menjadi ruang perkuliahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang kurun 1974-1980. Penyerahan dilakukan langsung oleh Abdul Aziz Lamadjido di penghujung masa jabatannya sebagai Bupati Donggala kala itu.
Setelah aktivitas perkuliahan IKIP Ujung Pandang boyongan ke Kampus Uninvesitas Tadulako di kawasan Bumi Bahari, Palu Barat, beberapa ruangan di kompleks bekas sekolah khusus etnis Tionghoa ini beralih fungsi jadi tempat tinggal hingga sekarang.
Walaupun kini hanya menyisakan gedung-gedung yang sudah kusam karena termakan zaman, kehadiran Chung Hwa Xue Xiao jadi bukti sumbangsih etnis Tionghoa di kota ini dalam memajukan dunia pendidikan, bukan hanya untuk golongan mereka, tapi juga kepada semua lapisan masyarakat.
Tionghoa Mandarin sekolah pendidikan Chung Hwa Xue Xiao kelenteng Alkhairaat melayu Permesta G30S Imlek